Penjelasan bagi Mereka Yang Belum Bisa Membedakan Antara Masalah Khilafiyyah dengan Ijtihadiyyah
Oleh : Ust. Muhammad Umar As-Sewed
Ketika sebagian pelaku maksiat diingatkan untuk menjauhi maksiatnya, kemudian orang yang mengingatkan tersebut ia katakan, “janganlah dirimu merasa paling suci sendiri”, apalah bedanya hal ini dengan orang yang diingatkan untuk menjauhi kesyirikan dan kebid’ahan yang hal itu dianggapnya suatu ibadah, kemudian orang yang mengingatkan tersebut ia katakan, “janganlah dirimu merasa benar sendiri”…
Semua mereka pukul rata, apakah perkara aqidah apakah perkara khilaf, mereka menggunakan satu kaedah mutlak. Tidak ada kebenaran yang hakiki, semua orang bisa berada pada suatu kebenaran, maka tidak boleh ada yang saling klaim berada diatas kebenaran, karena ‘bisa jadi’ dia berada diatas kesesatan.
kelompok yang paling ekstrim dalam masalah ini adalah ahli kalam, yakni orang-orang berpehamahan filsafat yang sesat, yang dianut J.I.L (jaringan iblis laknatullåh), yang membenarkan semua agama, menyatukan semua agama.. na’udzubillahi min dzaalik. dan ada kelompok yang tidak seekstrim kelompok pertama, tapi juga memiliki ’sedikit kesamaan’ dengan kelompok ini, namun tidak separah dengan kelompok pertama. kelompok ini bedanya, tetap berpegang teguh kepada al-islam sebagai agama yang haq, NAMUN, kelompok ini menyamaratakan segala permasalahan dalam islam itu sendiri.
Oleh : Ust. Muhammad Umar As-Sewed
Ketika sebagian pelaku maksiat diingatkan untuk menjauhi maksiatnya, kemudian orang yang mengingatkan tersebut ia katakan, “janganlah dirimu merasa paling suci sendiri”, apalah bedanya hal ini dengan orang yang diingatkan untuk menjauhi kesyirikan dan kebid’ahan yang hal itu dianggapnya suatu ibadah, kemudian orang yang mengingatkan tersebut ia katakan, “janganlah dirimu merasa benar sendiri”…
Semua mereka pukul rata, apakah perkara aqidah apakah perkara khilaf, mereka menggunakan satu kaedah mutlak. Tidak ada kebenaran yang hakiki, semua orang bisa berada pada suatu kebenaran, maka tidak boleh ada yang saling klaim berada diatas kebenaran, karena ‘bisa jadi’ dia berada diatas kesesatan.
kelompok yang paling ekstrim dalam masalah ini adalah ahli kalam, yakni orang-orang berpehamahan filsafat yang sesat, yang dianut J.I.L (jaringan iblis laknatullåh), yang membenarkan semua agama, menyatukan semua agama.. na’udzubillahi min dzaalik. dan ada kelompok yang tidak seekstrim kelompok pertama, tapi juga memiliki ’sedikit kesamaan’ dengan kelompok ini, namun tidak separah dengan kelompok pertama. kelompok ini bedanya, tetap berpegang teguh kepada al-islam sebagai agama yang haq, NAMUN, kelompok ini menyamaratakan segala permasalahan dalam islam itu sendiri.
Kebenaran di Sisi Allah Hanya Satu
Kita memaklumi terjadinya perbedaan dan perselisihan di kalangan shahabat رضي الله عنهم dan para ulama karena mereka seluruhnya adalah orang-orang yg berupaya untuk mencocoki kebenaran. Oleh karena itu ijtihad dan kesungguhan mereka untuk mencari yang paling benar mendapatkan pahala di sisi Allah.
Namun berbicara tentang kebenaran tetap hanya satu sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah صلى الله عليه وسلم:
Jika seorang hakim berijtihad dan tepat, maka dia mendapatkan dua pahala. Dan jika seorang hakim berijtihad dan tidak tepat, maka dia mendapatkan satu pahala.
Hadits di atas menunjukkan kalau ijtihad mereka tetap mendapatkan pahala, namun tetap ada yang benar dan ada yang salah, ada yang tepat dan ada pula yang menyimpang/keliru. Sehingga kita diperintahkan untuk mengambil mana yang lebih rajih dan mana yang lebih dekat pada kebenaran.
Allah سبحانه وتعالى berfirman:
"Maka (Dzat yang demikian) itulah Allah Rabb kalian yang sebenarnya; maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kalian dipalingkan (dari kebenaran)?" (Yunus: 32)
Qurthubi رحمه الله berkata: “Ayat ini memutuskan bahwa tidak ada selain haq dan batil kedudukan yang ketiga dalam masalah ini yaitu masalah tauhid dan demikian pula dalam masalah-masalah lain yang semisalnya seperti masalah-masalah prinsip yang lain maka tidak ada kebenaran kecuali hanya satu”. (al-Jami’ Li Ahkamil Qur’an, 8/336)
Para salafus shalih juga tidak berdalil dengan keumuman ayat di atas untuk semua masalah agama bahwa selain kebenaran adalah kebatilan. Dengan kata lain kebenaran hanya satu. (Zajrul Mutahawin, Hamd bin Ibrahim, hal. 36)
Karena itulah Imam Malik رحمه الله berkata tentang perbedaan para shahabat: “Tidak, demi Allah. Tidaklah kebenaran kecuali hanya satu. Apakah dua pendapat yang berbeda keduanya dapat dikatakan benar? Tidaklah kebenaran kecuali hanya satu. (Shifat Shalat Nabi, Syaikh al-Albani, hal. 61).
Lagi pula Allah سبحانه وتعالى memerintahkan agar kita jangan menyelisihi kebenaran dan melarang kita untuk berselisih setelah datang kebenaran yang jelas. Ini pun menunjukkan bahwa kebenaran di sisi Allah hanya satu.
Allah سبحانه وتعالى berfirman:
"Dan janganlah kalian menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat". (Ali Imran: 105)
Allah juga memerintahkan kita untuk bersatu dengan memegang tali Allah dan melarang untuk berpecah-belah. Ini pun menunjukkan bahwa kebenaran di sisi Allah hanya satu.
Allah سبحانه وتعالى berfirman:
"Dan berpeganglah kalian semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kalian bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian ketika kalian dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh musuhan, maka Allah mempersatukan hati kalian, lalu menjadilah kalian karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara; dan kalian telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kalian, agar kalian mendapat petunjuk". Ali Imran: 103)
Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: “Ayat-ayat yang melarang perselisihan dan berpecah-belah dalam agama mengandung cercaan kepadanya merupakan bukti yang jelas bahwa kebenaran di sisi Allah hanya satu. Sedangkan selainnya adalah kesalahan. Kalau saja semua pendapat itu benar, niscaya Allahd an rasul-Nya tidak melarang perselisihan dan mencecanya”. (Mukhtashar Shawaiqil Mursalah, Ibnul Qayyim, 2/566).
Bukti lain tentang kebenaran hanya satu adalah ayat yang menyatakan bahwa perselisihan bukan satu hal yang disyariatkan oleh Allah.
Allah سبحانه وتعالى berfirman:
"Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur’an? Kalau kiranya Al-Qur’an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapati pertentangan yang banyak di dalamnya". (an-Nisaa’: 82)
Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: “Allah mengabarkan bahwa perselisihan bukan dari sisi-Nya (syariat-Nya). Maka apa yang bukan dari sisi Allah adalah bukan merupakan kebenaran”. (Mukhtashar Shawaiqil Mursalah, Ibnul Qayyim, 2/566)
Bahkan jika perselihan terjadi antara dua nabi sekalipun –yang keduanya dimuliakan dan dipuji oleh Allah–, Allah tetap menyebutkan ada yang benar ijtihadnya dan ada pula yang keliru.
Allah سبحانه وتعالى berfirman:
"Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu, maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat); dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu dan telah Kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud. Dan Kamilah yang melakukannya". (al-Anbiyaa’: 7879)
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata: “Inilah dua nabi yang mulia. Keduanya memerintahkan pada satu wilayah dan menghukumi satu perkara yang sama. Namun Allah khususkan salah satu dari keduanya dengan pemahaman dan tetap memuji keduanya bahwa keduanya mendapatkan dari Allah ilmu dan hukum. Demikian pula para ulama –semoga Allah meridhainya– yang berijtihad, yang benar dari mereka mendapatkan dua pahala, sedangkan yang keliru mendapatkan satu pahala. Namun masing-masingnya adalah orang yang taat kepada Allah, karena upayanya dengan kemampuannya. Allah tidak membebani seseorang dengan sesuatu yang tidak mampu ilmunya. (Majmu’ Fatawa, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, 33/41)
Muhammad Amin asy-Syinqithi رحمه الله berkata: “Dalam ayat ini ada dua bukti kalau hukum yang diputuskan oleh keduanya adalah dengan berijtihad, bukan dengan wahyu. Dan bahwasanya Nabi Sulaiman lebih tepat ijtihadnya, maka ia berhak mendapatkan pujian karena ketepatan ijtihadnya. Adapun nabi Daud ijtihadnya tidak tepat, namun ia pun berhak mendapatkan pujian karena ijtihadnya. Ia tidak mendapatkan cercaan atau teguran karena ketidak-tepatannya….”
Kemudian beliau berkata: “Kalau saja masalah itu sudah ada wahyu yang turun, niscaya tidak akan terjadi perseisihan”. (Adwaul Bayan, asy-Syinqithi, 4/650)
Perhatikanlah! Syaikh asy-Syinqithi membedakan antara sesuatu yang sudah ada dalilnya yang jelas dari wahyu, maka tidak pantas terjadi perselisihan. Adapun yang menyelisihi wahyu adalah tercela dan tidak dianggap sebagai seorang mujtahid yang dihargai usaha ijtihadnya.
Diriwayatkan dari Abu Sa’id al-Khudry رضي الله عنه bahwa kaum Yahudi Bani Quraidhah meminta dihukumi oleh Saad dengan mengendarai seekor keledai. Ketika dekat dengan masjid Rasulullah صلى الله عليه وسلم, ia mengatakan: Bangunlah kalian untuk sayyid kalian. Kemudian Nabi صلى الله عليه وسلم berkata: “Apakah mereka meminta dihukumi olehmu?” Sa’ad pun berkata: “Bunuh semua orang-orang laki-laki dewasa dan jadikan tawanan semua wanita dan anak-anak”. Maka nabi صلى الله عليه وسلم bersabda:
Sungguh engkau telah menghukumi mereka dengan huku Allah yang Maha Tinggi kerajaan-Nya. (HR. Bukhari Muslim)
Demikianlah Rasulullah صلى الله عليه وسلم memuji keputusan Sa’ad dan menyatakan bahwa ijtihadnya tepat dan mencocoki hokum Allah.
Diriwayatkan pula bahwa Ibnu Ma’ud رضي الله عنه ketika diminta untuk menyetujui pendapat Abu Musa al-Asy’ari dalam masalah warisan anak perempuan dan anak anak perempuannya anak laki-laki dan saudara perempuan, yakni diberikan untuk anak perempuan setengah dans audara perempuan setengah. Ibnu Mas’ud menjawab: “Kalau begitu aku sesat dan aku tidak mendapatkan petunjuk. Aku memutuskan dengan apa yang telah diputuskan oleh Nabi yaitu untuk anak perempuan setengah, uantuk anak perempuannya anak laki-laki seperenam, sedangkan sisanya untuk saudara perempuan. Maka diberitakanlah jawaban ini kepada Abu Musa al-Asy’ari, maka ia berkata: “Jangan kalian Tanya kepadaku selama ahlul ilmi tersebut ada pada kalian!”(Atsar riwayat Bukhari)
Bahkan Ibnu Abbas رضي الله عنهما sempat menantang mubahalah ketika terjadinya perbedaan pendapat tentang hukum waris. Beliau رضي الله عنهما berkata: “Sungguh aku ingin mereka-mereka yang menyelisihi aku dalam masalah hukum waris ini berkumpul bersama dan meletakkan tangan-tangannya di tiang ini. Kemudian kita bermubahalah menjadikan laknat Allah pada orang-orang yang berdusta. (Atsar riwayat Abdurrazzaq dalam Mushannaf).
[Bulletin Manhaj Salaf Edisi: 134/Th. III tanggal 26 Safar 1428 H/16 Maret 2007 M]
Adakah Pengingkaran Dalam Masalah Khilafiyyah..?
Telah beredar di tengah kaum muslimin satu pemahaman yang menyatakan bahwa dalam masalah khilafiyyah (perkara yang masih diperselisihkan di kalangan ulama) tidak boleh adanya pengingkaran. Yakni selama perkara tersebut masih ada perselisian, maka kita tidak boleh saling mengingkari. Benarkah pendapat demikian?
Entah dari mana asal pemahaman tersebut. Namun bisa jadi kaidah ini muncul sebagai bahasa lain dari kaidah Ikhwanul Muslimin (IM) yang telah kita bantah pada edisi yang lalu: “Kita saling hormat-menghormati terhadap apa yang kita berbeda”. Kaidah ini telah muncul sejak dulu ketika kaum sufi enggan untuk menegakkan nahi mung-kar. Mereka selalu beralasan bahwa da lam masalah tersebut masih ada khila-fiyyah, “mereka juga punya dalil” dan seterusnya.
Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: “Ucapan mereka bahwa dalam masalah khilafiyyah tidak boleh ada pengingkaran adalah ucapan yang batil. Suatu pengingkaran itu bisa jadi mengarah pada ucapan, fatwa atau perbuatan. Adapun dalam masalah ucapan, jika ucapan tersebut menyelisihi sunnah atau ijma’ yang sudah dikenal, maka wajib diingkari menurut kesepakatan para ulama. Kalaupun tidak dalam bentuk pengingkaran, maka penjelasan le-mahnya pendapat tersebut atau bertentangannya dengan dalil, itu pun sesungguhnya merupakan pengingkaran.
Bagaimana mungkin seorang faqih mengatakan tidak ada pengingkaran dalam masalah khilafiyyah, sedangkan para pakar-pakar fiqh dari seluruh madzhab mengatakan dengan tegas batalnya keputusan hakim jika menyelisihi al-Qur’an dan as-Sunnah, walaupun mencocoki beberapa pendapat ulama.
Masuknya kerancuan ini adalah ke-tika mereka meyakini bahwa masalah khilafiyyah sama dengan masalah ijti-hadiyyah sebagaimana dipahami oleh berbagai golongan manusia yang tidak memiliki ilmu yang dalam”. (I’lamul Muwaqi’in, 3/288)
Lihatlah bagaimana Ibnul Qayyim رحمه الله membedakan antara masalah khilafiyyah dengan masalah ijtihadiyyah karena belum tentu perbedaan pendapat para ulama disebabkan oleh tidak adanya dalil dari al-Qur’an dan as-Sunnah. Bisa terjadi perbedaan di antara dua ulama ahlu sunnah karena yang satu telah sam pai kepadanya hadits yang shahih, se dangkan yang lain belum sampai kepadanya hadits tersebut seperti pendapat Abu Hanifah رحمه الله yang menyatakan bolehnya seorang wanita menikahkan dirinya (tan pa wali), karena belum sampainya hadits yang menyatakan tidak ada nikah tanpa wali.
Kita menyikapi berbeda antara Abu Hanifah رحمه الله yang tidak mendengar h dits tersebut dengan para pengikutnya yang taqlid buta walaupun sudah mem baca hadits “Tidak ada nikah tanpa wali”. Kita doakan semoga Allah سبحانه وتعالى meng ampuni Abu Hanifah dan memaafkan ke salahannya, namun kita tetap menging kari pengikutnya jika mereka memboleh kan seorang wanita nikah tanpa wali.
Ibnul Qayyim رحمه الله mendefinisikan masalah ijtihadiyyah adalah perkara yang tidak ada kejelasan dalilnya. (I’la-mul Muwaqi’in, 3/287; Lihat Dharu-rarul Ihtimam, hal. 103)
Ketahuilah bahwa masalah khilafiyyah itu bertingkat tingkat. Ada ikhtilaf yang disebabkan karena perbedaan mak na kalimat-kalimatnya saja, ada pula ikthtilaf karena salah satu pendapat ter sebut jelas kelemahannya. Dalam khilafiyyah yang seperti ini kita wajib meng ingkari pendapat yang lemah bahkan dapat membatalkan keputusan seorang hakim. Namun di antara masalah khilafiyyah ada perkara-perkara yang rumit yang dalil kedua belah pihak sangat kuat dan pendapat-pendapat mereka saling berdekatan dan dasar dari masing-masingnya adalah pada pemahaman dan pengambilan hukum syar’i. Inilah yang disebut masalah ijtihadiyyah. (Lihat Dharurarul Ihtimam, hal. 100)
Bagaimana kita menyikapinya?
Yang wajib dalam masalah ini adalah:
Pertama, perlunya ada saling nasehat-menasehati antara kedua orang yang berbeda pendapat dengan cara diskusi ilmiah yang membuahkan kebenaran dengan menjelaskan sisi pendalilan atau sudut pandang dan dalil dari masing-masing pendapat.
Kedua, jika tidak puas salah satu nya dengan apa yang dikemukakan oleh saudaranya, maka janganlah membawa pada kekerasan, pengingkaran dan per pecahan.
Ketiga, jika ketidak puasannya di bangun bukan atas dasar hujjah, namun karena ta’ashub madzhab atau hawa naf su dan sejenisnya maka perlu diingkari karena yang menjadi ukuran adalah pe nyelisihannya terhadap dalil. (Lihat Dharuratul Ihtimam, hal. 101)
Diriwayatkan dalam dua kitab sha hih bahwasanya Nabi صلى الله عليه وسلم menye ru para shahabatnya ketika selesai pe rang Ahzab dengan kemenangan. Beliau صلى الله عليه وسلم bersabda:
لاَ يُصَلِّيَنَ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلاَّ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ.
Jangan sekali-kali salah seorang kalian shalat ashar, kecuali di tempat Bani Quraidhah!
Namun ketika manusia khawatir kehilangan waktu ashar, maka sebagian mereka pun ada yang shalat di tengah jalan sebelum tempat bani Quraidhah. Sedang-kan sebagian lainnya berkata: “Tidak, kami tidak akan shalat, kecuali di tempat yang telah diperintahkan Rasulullah صلى الله عليه وسلم kepada kami, walaupun telah lewat waktu”. Dan Rasulullah صلى الله عليه وسلم pun tidak menyalahkan kedua belah pihak. (HR. Bukhari dengan Fathul Bary, 7/3407; Muslim dengan Syarh Nawawi, 12/97)
Demikianlah masing masing dari para shahabat mengerjakan apa yang diyakininya benar menurut masing-masing mereka, yang satu tidak menyalahkan yang lainnya. Dan ini dipahami oleh para ulama adalah masalah ijtihadiyyah. Berbeda dengan apa yang dipahami oleh mu’tazilah bahwa ini menunjukkan bolehnya memahami ayat dan hadits de ngan dua cara: tekstual dan kontekstual, dan antara satu dengan yang lainnya tidak boleh saling menyalahkan.
Pendapat mu’tazilah ini adalah pe dapat yang batil. Sebab hukum asal dari ucapan Allah dalam al-Qur’an dan ucap an Rasulullah صلى الله عليه وسلم dalam hadits adalah dhahir (teks)nya, kecuali jika ada dalil lain yang menunjukkan makna lain selain yang dhahir. Ini adalah kaidah yang dikenal oleh para ulama sejak dulu. Oleh karena itulah mereka memahami kisah para shahabat di atas pada masalah ijtihadiyyah.
Imam Sufyan ats-Tsauri رحمه الله berkata: “Jika engkau melihat seseorang beramal dengan satu amal ibadah yang masih diperselisihkan, sedangkan eng-kau berpendapat lain, maka jangan eng-kau larang dia!” (al-Faqih wal Muta-faqih, oleh al-Khathib, 2/69; Lihat kitab Dharuratul Ihtimam, hal. 102)
Ucapan yang seperti ini dari para ulama tentunya diterapkan dalam konteks masalah ijtihadiyyah, bukan semua masalah khilafiyyah.
Yahya bin Sa’id al-Anshari رحمه الله berkata: “Para ahli fatwa masih terus mengeluarkan fatwa mereka. Sebagian menyatakan halal dan sebagian lainnya menyatakan haram (dengan ijtihad me-reka). Maka tidaklah yang menghalal-kan berpendapat bahwa yang mengha-ramkan akan binasa. Demikian pula se-baliknya, tidaklah yang mengharamkan berpendapat bahwa yang menghalalkan akan binasa. (Jami’ Bayanil Ilmi wa Fadhlihi, Ibnu Abdil Barr; lihat Dha-ruratul Ihtimam,hal. 102)
Seluruh ucapan ulama di atas ada lah dalam masalah ijtihadiyyah yang muncul dari para ulama yang memang layak untuk berijtihad. Dan dalam masa lah yang seperti ini tidak ada penging karan kecuali sekedar diskusi dan saling menasehati. (Dharuratul Ihtimam,hal. 102)
Ada pun dalam masalah yang se orang ulama tergelincir padanya, atau salah dalam berfatwa menyelisihi nash yang sharih (maknanya) dan shahih (riwayatnya), maka para ulama yang me ngetahui kesalahan tersebut senantiasa mengingkarinya. Demikian keadaan me reka sejak masa para shahabat.
Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: “… bahkan menurut para ahli hadits orang yang meminum nabidz*) –yang masih diperselisihkan— dihukum dengan hu-kum had (cambuk), ini adalah lebih dari pada sekedar pengingkaran. Bahkan menurut fuqaha Madinah mereka di-anggap fasiq dan tidak diterima per-saksiannya. Ini membantah pendapat orang yang berkata: “Tidak ada peng-ingkaran dalam masalah khilafiyyah”. Bahkan pendapat ini menyelisihi kese-pakatan seluruh para imam. Tidak ada seorang imam pun dari imam-imam kaum muslimin yang berpendapat demi-kian. (I’lamul Muwaqi’in, 3/229; Lihat Dharuratul Ihtimam, hal. 103)
Nabidz yang dimaksud adalah khamr yang dibuat dari perasan kurma atau kismis atau madu atau gandum. Namun setelah fermentasi dan menjadi khamr diproses kembali hingga tidak memabukkan.
Pernah terjadi satu kisah mengenai Nabidz ini yang diceritakan oleh Abdullah ibnul Mubarak. Beliau berkata: Ketika aku di Kufah, beberapa orang mendebat aku dalam masalah nabidz yang diperselisihkan. Aku katakan kepada mereka: “Marilah kemari dan silakan salah seorang dari kalian menyampaikan hujjahnya dari siapapun yang ia sukai dari para shahabat nabi صلى الله عليه وسلم yang membolehkannya”.
Maka mereka pun membawakan hujjah-hujjah, namun tidaklah mereka membawakan satu ucapan shahabat pun, kecuali kami sebutkan kelemahan sanadnya. Maka tidak tersisa kecuali ri wayat dari Abdullah ibnu Mas’ud. Namun ternyata tidaklah hujjah mereka dengan ucapan Ibnu Mas’ud kecuali jus tru menguatkan haramnya nabidz.
Aku katakan kepada yang membo lehkan: “Wahai orang bodoh, anggaplah Ibnu Mas’ud ada di sini dan duduk di hadapan kita kemudian berkata bahwa nabidz itu untukmu halal. Bukankah te-tap apa yang disifatkan oleh Nabi صلى الله عليه وسلم dan para shabatnya رضي الله عنهم tentang larangan nabidz semestinya mem-buatmu takut dan menghindari?”
Kemudian salah seorang mereka berkata: “Wahai Abu Abdirrahman (yakni Ibnu. Mubarak) apakah berarti an-Nukhai, asy-Sya’bi –disebut pula imam-imam yang lainnya—mereka me-minum yang haram?”
Aku katakan kepada mereka: “Tinggalkan nama-nama seseorang da-lam berdiskusi! Bisa jadi seorang dalam Islam memiliki keutamaan-keutamaan yang banyak namun ia tergelincir da-lam suatu masalah, apakah boleh kita berdalil dengan pendapat orang itu?
Kalau tetap kalian menolak, maka bagaimana pendapatmu tentang Atha’, Thawus, Jabir bin Zaid, Sa’id bin Jubair dan Ikrimah?”
Mereka menjawab: “Mereka adalah orang-orang mulia”.
Aku katakan: “Bagaimana penda-patmu kalau satu dirham ditukar dengan 2 dirham secara kontan?”
Mereka menjawab: “Haram”.
Aku katakan: “Tapi mereka (orang-orang yang mulia tadi –pent.) berpendapat halal, apakah mereka mati dalam keadaan memakan yang haram?”
Maka terdiamlah mereka dan patahlah hujjah-hujjah mereka.” (Lihat Dharuratul Ihtimam, hal. 103-104)
(Diambil dari Dharuratul Ihti-mam, Abdus Salam Ibnu Barjis, hal. 98-104)
[Buletin Manhaj Salaf, Edisi: 136/Th. 3 Tanggal 18 Rabi’ul Awwal 1428 H/06 April 2007 M]
Sumber : http://kaahil.wordpress.com/2010/07/31/merasa-paling-benar-sendiri-atau-tidak-ada-kebenaran-yang-hakiki-penjelasan-bagi-mereka-yang-belum-bisa-membedakan-antara-masalah-khilafiyyah-dengan-ijtihadiyyah/














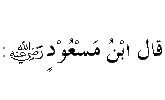




















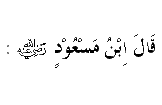














Comments (0)
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.