Bismillah,
Syaikh Al-Qasimi rahimahullah dalam kitab Qawâid At-Tahdîts, hal: 94 mengatakan bahwa pendapat tersebut diceritakan oleh Ibnu Sayyidin Nas dalam ‘Uyunul Atsar dari Yahya bin Ma’in dan Fathul Mughits beliau menyandarkannya kepada Abu Bakr bin ‘Arabi. Pendapat ini juga merupakan pendapat Bukhari, Muslim dan Ibnu Hajm.
Maka hadis dha’if dalam keadaan semacam ini boleh diamalkan dalam keutamaan amal, karena hal itu bukan pensyari’atan amal itu tetapi semata-mata sebagai keterangan tentang pahala khusus yang diharapkan oleh pelakunya. Oleh karena itu ucapan sebagaian ulama dimasukkan seperti ini. Seperti Syaikh Ali Al-Qari rahimahullah dalam Al-Mirqah 2/381 mengatakan bahwa hadis lemah diamalkan dalam perkara keutamaan amal walaupun tidak didukung secara ijma’ sebagaimana keterangan Imam An-Nawawi, yaitu pada amal yang shahih berdasarkan Al-Kitab dan As-Sunnah.
Maka dengan dasar inilah maka beramal dengan hadis dha’if diperbolehkan jika telah adanya hadis shahih yang menunjukkan disyari’atkannya amal itu. Akan tetapi kebanyakan orang yang berpendapat seperti itu tidak dimaksudkan makna seperti itu. Buktinya kita menyaksikan mereka beramal dengan hadis-hadis dha’if yang tidak terkandung dalam hadis-hadis shahih, seperti Imam An-Nawawi dan yang mengikutinya menganggap sunnah menjawab ucapan orang yang mengumandangkan iqamah ketika mengucapkan dua kalimat syahadat (=qadqa matis shalah, qadqa matis shalah) dengan ucapan “aqamahala wa adamaha” (=semoga Allah menegakkannya dan melazimkannya), padahal hadis tentang masalah ini adalah dha’if . [Kelemahan hadis ini dapat dilihat pada; Irwa’ul Ghalil 241. Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani rahimahullah; Ilmu Ushulil Bida’, hal: 157. Syaikh ‘Ali Hasan bin Adul Hamid.]
Amal ini tidak ditetapkan pensyari’atannya kecuali pada hadis dha’if tersebut. Meskipun demikian mereka menganggap hal itu merupakan suatu sunnah. Padahal perkara sunnah adalah salah satu hukum diantara kelima hukum (yakni: wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram) yang harus ditetapkan berdasarkan dalil.
Adapun yang terpenting disini adalah hendaklah orang-orang yang menyelisihi hal ini mengetahui bahwa beramal dengan hadis dha’if dalam perkara keutamaan amal tidak mutlak menurut orang-orang yang berpendapat dengannya. Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata dalam Tabyanul Ujab, hal: 3-4 bahwa para ahli ilmu telah bermudah-mudah dalam membawakan hadis-hadis tentang keutamaan amal walaupun memiliki kelemahan selama tidak maudhu’ (=palsu). Seharusnya hal ini diberi syarat yaitu orang yang beramal dengannya menyakini bahwa hadis itu lemah dan tidak memasyhurkannya sehingga orang tidak beramal dengan hadis dha’if dan mensyari’atkan apa yang tidak disyari’atkan atau sebagian orang-orang jahil (=bodoh) menyangka bahwa hadis itu adalah shahih.
Hal ini juga ditegaskan oleh Al-Ustadz Abu Muhammad bin Abdus Salam dan lain- lain. Hendaknya setiap orang khawatir jika termasuk dalam ancaman Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa salam :
مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ
“Barangsiapa menceritakan dariku satu hadis yang dianggap hadis itu dusta, maka dia termasuk seorang pendusta” [Untuk lebih jelasnya lihat permasalahan ini pada kitab Syarh Shahih Muslim, juz: 1, bagian muqadimah. Imam An-Nawawi Ad- Damsiqi rahimahullah.]
Maka bagaimana orang yang mengamalkannya?!. Tidak ada perbedaan antara mengamalkan suatu hadis dalam perkara hukum atau dalam perkara keutamaan amal, sebab semuanya adalah syari’at.
Inilah tiga syarat penting diperbolehkannya beramal dengan hadis-hadis dha’if dalam keutamaan amal;- Hadis itu tidak maudhu’ (=palsu).
Berkata Syaikh Muhaddits (ahli hadis) Muhammad Nashiruddin Al-Albani rahimahullah: ”Di kalangan ahli ilmu dan para penuntut ilmu ini telah masyhur bahwa hadis dha’if (lemah) boleh diamalkan dalam fadlailul ‘amal (keutamaan amal). Mereka menyangka bahwa perkara ini tidak diperselisihkan. Bagaimana tidak, Imam Nawawi rahimahullah menyatakan dalam berbagai kitab beliau bahwa hal ini telah disepakati. (Seperti dalam kitab Arba’în Nawawi, pent.) Tetapi pernyataan beliau itu terbantah karena perselisihan dalam hal ini ma’rûf. Sebagian besar para muhaqiq (peneliti) berpendapat bahwa hadis dha’if tidak boleh diamalkan secara mutlak, baik dalam perkara-perkara hukum maupun keutamaan-keutamaan.
Syaikh Al-Qasimi rahimahullah dalam kitab Qawâid At-Tahdîts, hal: 94 mengatakan bahwa pendapat tersebut diceritakan oleh Ibnu Sayyidin Nas dalam ‘Uyunul Atsar dari Yahya bin Ma’in dan Fathul Mughits beliau menyandarkannya kepada Abu Bakr bin ‘Arabi. Pendapat ini juga merupakan pendapat Bukhari, Muslim dan Ibnu Hajm.
Saya (Syaikh Al-Albani) katakan bahwa inilah yang benar menurutku, tidak ada keraguan padanya karena bebarapa perkara;pertama: Hadis dha’if hanya mendatangkan sangkaan yang salah (zhannul marjûh). Tidak boleh beramal dengannya berdasarkan kesepakatan. Barangsiapa mengecualikan boleh beramal dengan hadis dha’if dalam keutamaan amal, hendaknya dia mendatangkan bukti, sungguh sangat jauh!. Kedua: Yang aku pahami dari ucapan mereka tentang keutamaan amal yaitu amal-amal yang telah disyari’atkan berdasarkan hadis shahih, kemudian ada hadis lemah yang menyertainya yang menyebutkan pahala khusus bagi orang yang mengamalkannya.
Maka hadis dha’if dalam keadaan semacam ini boleh diamalkan dalam keutamaan amal, karena hal itu bukan pensyari’atan amal itu tetapi semata-mata sebagai keterangan tentang pahala khusus yang diharapkan oleh pelakunya. Oleh karena itu ucapan sebagaian ulama dimasukkan seperti ini. Seperti Syaikh Ali Al-Qari rahimahullah dalam Al-Mirqah 2/381 mengatakan bahwa hadis lemah diamalkan dalam perkara keutamaan amal walaupun tidak didukung secara ijma’ sebagaimana keterangan Imam An-Nawawi, yaitu pada amal yang shahih berdasarkan Al-Kitab dan As-Sunnah.
Maka dengan dasar inilah maka beramal dengan hadis dha’if diperbolehkan jika telah adanya hadis shahih yang menunjukkan disyari’atkannya amal itu. Akan tetapi kebanyakan orang yang berpendapat seperti itu tidak dimaksudkan makna seperti itu. Buktinya kita menyaksikan mereka beramal dengan hadis-hadis dha’if yang tidak terkandung dalam hadis-hadis shahih, seperti Imam An-Nawawi dan yang mengikutinya menganggap sunnah menjawab ucapan orang yang mengumandangkan iqamah ketika mengucapkan dua kalimat syahadat (=qadqa matis shalah, qadqa matis shalah) dengan ucapan “aqamahala wa adamaha” (=semoga Allah menegakkannya dan melazimkannya), padahal hadis tentang masalah ini adalah dha’if . [Kelemahan hadis ini dapat dilihat pada; Irwa’ul Ghalil 241. Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani rahimahullah; Ilmu Ushulil Bida’, hal: 157. Syaikh ‘Ali Hasan bin Adul Hamid.]
Amal ini tidak ditetapkan pensyari’atannya kecuali pada hadis dha’if tersebut. Meskipun demikian mereka menganggap hal itu merupakan suatu sunnah. Padahal perkara sunnah adalah salah satu hukum diantara kelima hukum (yakni: wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram) yang harus ditetapkan berdasarkan dalil.
Betapa banyak perkara-perkara yang mereka anggap disyari’atkan dan disunnahkan bagi manusia hanya didasari dengan hadis-hadis lemah yang tidak ada asal pensyari’atannya dalam hadis shahih. Akan tetapi disini tidak mungkin untuk mencantumkan sebagai contoh, cukuplah salah satu contoh yang telah aku sebutkan.
Adapun yang terpenting disini adalah hendaklah orang-orang yang menyelisihi hal ini mengetahui bahwa beramal dengan hadis dha’if dalam perkara keutamaan amal tidak mutlak menurut orang-orang yang berpendapat dengannya. Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata dalam Tabyanul Ujab, hal: 3-4 bahwa para ahli ilmu telah bermudah-mudah dalam membawakan hadis-hadis tentang keutamaan amal walaupun memiliki kelemahan selama tidak maudhu’ (=palsu). Seharusnya hal ini diberi syarat yaitu orang yang beramal dengannya menyakini bahwa hadis itu lemah dan tidak memasyhurkannya sehingga orang tidak beramal dengan hadis dha’if dan mensyari’atkan apa yang tidak disyari’atkan atau sebagian orang-orang jahil (=bodoh) menyangka bahwa hadis itu adalah shahih.
Hal ini juga ditegaskan oleh Al-Ustadz Abu Muhammad bin Abdus Salam dan lain- lain. Hendaknya setiap orang khawatir jika termasuk dalam ancaman Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa salam :
مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ
“Barangsiapa menceritakan dariku satu hadis yang dianggap hadis itu dusta, maka dia termasuk seorang pendusta” [Untuk lebih jelasnya lihat permasalahan ini pada kitab Syarh Shahih Muslim, juz: 1, bagian muqadimah. Imam An-Nawawi Ad- Damsiqi rahimahullah.]
Maka bagaimana orang yang mengamalkannya?!. Tidak ada perbedaan antara mengamalkan suatu hadis dalam perkara hukum atau dalam perkara keutamaan amal, sebab semuanya adalah syari’at.
Inilah tiga syarat penting diperbolehkannya beramal dengan hadis-hadis dha’if dalam keutamaan amal;
- Orang yang mengamalkannya mengetahui bahwa hadis itu adalah dha’if.
- Tidak memasysyhurkan untuk beramal dengannya.
Akan tetapi sangat disayangkan kita menyaksikan kebanyakan ulama, lebih-lebih orang awam meremehkan syarat-syarat ini. Mereka mengamalkan suatu hadis tanpa mengetahui kelemahannya, mereka tidak mengetahui apakah kelemahannya ringan atau sangat parah sehingga (hadis) tersebut tidak boleh diamalkan. Kemudian mereka memasyhurkannya sebagaimana halnya beramal dengan hadis shahih!. Oleh karena itu banyak ibadah-ibadah dikalangan kaum Muslimin yang tidak shahih dan memalingkan mereka dari ibadah-ibadah yang shahih yang diriwayatkan dengan sanad-sanad (=jalan, pent) yang shahih.
Kemudian syarat-syarat tersebut menguatkan pendapat kami bahwa sebagian besar ulama tidak menginginkan makna yang kami anggap kuat tadi, sebab satupun diantara syarat-syarat itu tidak diterapkan sebagaimana yang tampak.
Menurutku (Syaikh Al-Albani), Al-Hafizh Ibnu Hajar cenderung kepada tidak boleh beramal dengan hadis dha’if berdasarkan ucapan beliau yang telah lewat bahwa tidak ada perbedaan antara mengamalkan suatu hadis dalam perkara hukum atau dalam keutamaan amal sebab semuanya adalah syari’at.
Inilah yang haq, karena hadis dha’if yang tidak ada penguatnya kemungkinan adalah maudhu’ (=palsu), bahkan umumnya palsu dan mungkar. Hal ini ditegaskan oleh sebagian ulama. Orang yang membawakan hadis dha’if termasuk dalam ucapan Nabi Shalallahu ‘alaihi wa salam:”…yang dianggap hadis itu dusta”, yaitu dengan menampakkan demikian. Oleh karena itu Al-Hafizh menambahkan dengan ucapannya: ”Maka bagaimana dengan orang yang mengamalkannya”.
Hal ini dikuatkan dengan perkataan Ibnu Hibban bahwa setiap orang yang ragu terhadap apa yang dia riwayatkan, shahih atau tidak shahih, maka dia termasuk dalam hadis ini. Dan kita katakan seperti perkataan Al-Hafizh (Ibnu Hajar): ”Maka bagaimanakah dengan orang yang mengamalkannya”.
Adapun jika ucapan beliau dimaksudkan kepada larangan memakai hadis maudhu’ (palsu) dan tidak ada perbedaan antara perkara hukum dan keutamaan adalah sangat jauh dari konteks ucapan Al-Hafizh, sebab ucapan beliau adalah dalam pembahasan hadis dha’if, bukan maudhu’ sebagaimana hal itu tidak tersembunyi.
Al-Hafizh tidaklah menyatakan dengan tegas bahwa dia menyetujui mereka dalam membolehkan (beramal dengan hadis-hadis yang dha’if) dengan syarat-syarat itu. Bahkan di akhir ucapan beliau menegaskan sebaliknya seperti yang telah kami terangkan.
Kesimpulannya, bahwa beramal dengan hadis dha’if dalam perkara keutamaan amal tidak diperbolehkan sebab menyelisihi hukum asal dan tidak ada dalilnya. Orang yang membolehkannya harus memperhatikan syarat-syarat itu ketika mengamalkan hadis dha’if.
[Tamâmul Minnah Fî Ta’lîq Fiqh Sunnah, hal: 34-38. Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani rahimahullah. Dinukil dari majalah Salafy edisi: XXIII/Ramadlan/1418H/1996, hal: 23-25.]
- Tidak memasysyhurkan untuk beramal dengannya.
Akan tetapi sangat disayangkan kita menyaksikan kebanyakan ulama, lebih-lebih orang awam meremehkan syarat-syarat ini. Mereka mengamalkan suatu hadis tanpa mengetahui kelemahannya, mereka tidak mengetahui apakah kelemahannya ringan atau sangat parah sehingga (hadis) tersebut tidak boleh diamalkan. Kemudian mereka memasyhurkannya sebagaimana halnya beramal dengan hadis shahih!. Oleh karena itu banyak ibadah-ibadah dikalangan kaum Muslimin yang tidak shahih dan memalingkan mereka dari ibadah-ibadah yang shahih yang diriwayatkan dengan sanad-sanad (=jalan, pent) yang shahih.
Kemudian syarat-syarat tersebut menguatkan pendapat kami bahwa sebagian besar ulama tidak menginginkan makna yang kami anggap kuat tadi, sebab satupun diantara syarat-syarat itu tidak diterapkan sebagaimana yang tampak.
Menurutku (Syaikh Al-Albani), Al-Hafizh Ibnu Hajar cenderung kepada tidak boleh beramal dengan hadis dha’if berdasarkan ucapan beliau yang telah lewat bahwa tidak ada perbedaan antara mengamalkan suatu hadis dalam perkara hukum atau dalam keutamaan amal sebab semuanya adalah syari’at.
Inilah yang haq, karena hadis dha’if yang tidak ada penguatnya kemungkinan adalah maudhu’ (=palsu), bahkan umumnya palsu dan mungkar. Hal ini ditegaskan oleh sebagian ulama. Orang yang membawakan hadis dha’if termasuk dalam ucapan Nabi Shalallahu ‘alaihi wa salam:”…yang dianggap hadis itu dusta”, yaitu dengan menampakkan demikian. Oleh karena itu Al-Hafizh menambahkan dengan ucapannya: ”Maka bagaimana dengan orang yang mengamalkannya”.
Hal ini dikuatkan dengan perkataan Ibnu Hibban bahwa setiap orang yang ragu terhadap apa yang dia riwayatkan, shahih atau tidak shahih, maka dia termasuk dalam hadis ini. Dan kita katakan seperti perkataan Al-Hafizh (Ibnu Hajar): ”Maka bagaimanakah dengan orang yang mengamalkannya”.
Inilah penjelas dari maksud ucapan Al-Hafizh Ibnu Hajar tersebut.
Adapun jika ucapan beliau dimaksudkan kepada larangan memakai hadis maudhu’ (palsu) dan tidak ada perbedaan antara perkara hukum dan keutamaan adalah sangat jauh dari konteks ucapan Al-Hafizh, sebab ucapan beliau adalah dalam pembahasan hadis dha’if, bukan maudhu’ sebagaimana hal itu tidak tersembunyi.
Apa yang kami sebutkan tidak menafi’kan (=meniadakan) bahwa Al-Hafizh (Ibnu Hajar) menyebutkan syarat-syarat itu untuk mengamalkan hadis dha’if. Sebab kita katakan bahwa Al-Hafizh menyebutkan perkataan itu kepada orang-orang yang membolehkan memakai hadis dha’if dalam perkara keutamaan selama tidak maudhu’ (=palsu). Seakan-akan beliau berkata kepada mereka: ”Jika kalian berpendapat demikian, maka seharusnya kalian menerapkan syarat-syarat ini”.
Al-Hafizh tidaklah menyatakan dengan tegas bahwa dia menyetujui mereka dalam membolehkan (beramal dengan hadis-hadis yang dha’if) dengan syarat-syarat itu. Bahkan di akhir ucapan beliau menegaskan sebaliknya seperti yang telah kami terangkan.
Kesimpulannya, bahwa beramal dengan hadis dha’if dalam perkara keutamaan amal tidak diperbolehkan sebab menyelisihi hukum asal dan tidak ada dalilnya. Orang yang membolehkannya harus memperhatikan syarat-syarat itu ketika mengamalkan hadis dha’if.
Wallâhu Muwâfiq.
Demikian perkataan Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani rahimahullah.
[Tamâmul Minnah Fî Ta’lîq Fiqh Sunnah, hal: 34-38. Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani rahimahullah. Dinukil dari majalah Salafy edisi: XXIII/Ramadlan/1418H/1996, hal: 23-25.]
Sumber : http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/%3Fp%3D516/?paged=4














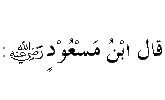




















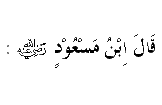














Comments (0)
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.