Oleh : Ustadz Abu Humaid Arif Syarifuddin
Di dalam kehidupan sehari-harinya seseorang tidak terlepas dari beban dan tanggungan. Di antara tanggungan yang mungkin menimpanya ialah hutang. Terutama ketika kondisi yang mendesak dan amat membutuhkan, atau kondisi-kondisi lainnya. Baik hutang tersebut terkait dengan hak manusia ataupun yang terkait dengan hak Allah. Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur masalah ini, sebagaimana telah tertuang dalam Kitabullah maupun Sunnah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam.
Adapun yang terkait hak manusia, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam sendiri pernah berhutang. Seperti pernah diceritakan oleh Aisyah Radhiyallahu ‘anha.
“Bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan harga pembayaran dibelakang (hutang) dan memberi jaminan dengan baju besi milik beliau” [Hadits Riwayat Bukhari 2386 –Fathul Bari- dan Muslim 1603]
Hadits tersebut menunjukkan adanya dalil bolehnya bermuamalah dengan ahli dzimmah (kafir dzimmi), dan boleh memberi suatu jaminan untuk hutang di saat mukim.[1]
Meski Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam berhutang, beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah orang yang senantiasa ingin bersegera dalam membayar hutangnya dan melebihkan pembayarannya. Jabir Radhiyallahu ‘anhu mengisahkan.
“Aku mendatangi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika beliau di Masjid –Mis’ar (perawi dalam sanad) berkata : Saya kira ia menyebut waktu Dhuha-. Lalu Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam memiliki hutang kepadaku. Maka beliau melunasinya dan memberiku tambahan”. [Hadits Riwayat Al-Bukhari 2394 –Fathul Bari- dan Muslim 715]
Demikianlah seharusnya setiap muslim mencontoh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Sehingga, hutang yang menjadi tanggungan diri seorang muslim, hendaknya segera ditunaikan bila telah memiliki harta yang dapat untuk melunasinya, tidak mengulur-ulurnya, karena hal itu termasuk bentuk kezhaliman. Hutang ini tetap akan menjadi tanggungannya, sampai ia mati sekalipun. Jika belum dilunasi, maka ruhnya akan tergantung sampai terlunasi hutangnya tersebut. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.
“Penguluran (hutang) oleh orang yang mampu (membayar) adalah kezhaliman” [Hadits Riwayat Al-Bukhari 2400 –Fathul Bari- dan Muslim 1564]
Beliau Shallalalhu ‘alaihi wa sallam juga bersabda.
“Jiwa (ruh) seorang mukmin tergantung karena hutangnya, sampai terlunasi” [Hadits Riwayat At-Tirmidzi 1078 dan Ibnu Majah 2413, dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu. Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani di dalam Shahihul Jami’ 6779]
Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah tidak mau menyalati jenazah seseorang, karena si mayit tersebut masih memiliki tanggungan hutang. Salamah bin Al-Akwa Radhiyallahu ‘anhu menuturkan.
“Bahwasanya, pernah dihadapkan kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam seorang jenazah untuk beliau shalati. Lalu beliau bertanya, “Apakah dia punya hutang?” Mereka menjawab, “Tidak”, maka beliau pun menyalatinya. Kemudian didatangkan kepada beliau jenazah yang lain, lalu beliau bertanya, “Apakah dia punya hutang?”, Mereka menjawab, “Ya” maka beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “Shalatilah teman kalian ini oleh kalian”. Abu Qatadah berkata, “Wahai Rasulullah. Saya yang akan melunasi hutangnya”, maka beliau pun mau menyalatinya” [Hadits Riwayat Al-Bukhari 2295 –Fathul Bari-]
Jadi, jika seseorang meninggal, di antara hak yang harus ditunaikan sebelum dilakukan pembagian warisan dari harta yang ditinggalkan untuk para ahli warisnya ialah melunasi hutang-hutang si mayit bila ia meninggalkan hutang, baik hutang yang terkait dengan hak Allah maupun hak manusia. Meskipun ketika melunasi hutang-hutangnya tersebut sampai menghabiskan seluruh harta yang ditinggalkannya. [2]
Akan tetapi, jika harta si mayit tersebut tidak mencukupi untuk melunasi hutang-hutangnya, maka apa yang harus dilakukan ?
[1]. Jika hutang-hutangnya berkaitan dengan hak manusia, maka dibolehkan bagi wali mayit untuk meminta pengampunan dari para pemilik harta hutang atas hutang-hutang si mayit kepada mereka, baik sebagian maupun keseluruhan. Hal ini terisyaratkan dalam kisah yang dialami oleh Jabir Radhiyallahu ‘anhu ketika ayahnya terbunuh di medan perang Uhud, sementara ia menanggung hutang. Dia meminta kepada para pemilik harta hutang untuk membebaskan sebagian hutang ayahnya, tetapi mereka menolak dan tetap berkeinginan untuk mengambil hak mereka. Akhirnya Jabir Radhiyallahu ‘anhu mendatangi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam (dan memintanya menyelesaikan masalah tersebut), maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam meminta kepada mereka agar mau meneriman kurma-kurma yang ada di kebun Jabir Radhiyallahu ‘anhu sebagai pembayarannya, dan menghalalkan (membebaskan) sebagian hutang ayahnya, tetapi mereka menolak. [Lihat Shahih Al-Bukahri, hadits 2395 dan 2405 – Fathul Bari]
Dari kisah diatas terdapat dalil, bahwa wali mayit boleh meminta kepada para pemilik harta hutang untuk mebebaskan hutang-hutang si mayit. Dan pemilik harta, boleh membebaskan sebagian atau seluruh hutang si mayit, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Baththal dan Ibnu Munayyir. [Lihat Fathul Bari, 3/73]
Dan dari kisah diatas, juga terpahami bahwa bila si mayit tidak memiliki harta yang cukup untuk melunasi hutang-hutangnya, maka dilunasi oleh walinya, atau kerabatnya. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadits yang dituturkan Sa’ad bin Athwal Radhiyallahu ‘anhu, ketika Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengatakan kepadanya.
“Sesungguhnya saudaramu tertahan (ruhnya) karena hutangnya, maka lunasilah hutangnya”. Kemudian Sa’ad berkata, “Wahai Rasulullah. Aku telah melunasi semuanya, kecuali dua dinar yang diakui oleh seorang wanita, sementara dia tidak punya bukti”. Maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “Berilah dia, karena dia berhak” [Hadits Riwayat Ibnu Majah, 2433, Ahmad 5/7 dan Al-Baihaqi 10/142. Dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam shahih Ibnu Majah] [3]
[2]. Namun, jika tidak ada seorangpun dari keluarga atau kerabat mayit yang bisa melunasi hutang-hutangnya, maka negara atau pemerintah yang menanggung pelunasan hutangnya, [4] diambilkan dari Baitul Mal.
Dikatakan oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam.sebagai pemimpin kaum muslimin.
“Aku lebih berhak menolong kaum Mukminin dari diri mereka sendiri. Jika ada seseorabng dari kaum Mukminin yang meninggal, dan meninggalkan hutang maka aku yang akan melunasinya…” [Hadits Riwayat Al-Bukhari 2298 –Fathul Bari- dan Muslim 1619 dari Abu Haurairah Radhiyallahu ‘anhu]
Maksud Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam ialah, akan melunasinya dari harta Baitul Mal, yang terdiri dari ghanimah (harta rampasan perang), jizyah (dari orang kafir yang berada dalam naungan kaum Muslimin), infak atau shadaqah serta zakat. [5]
Sebagiamana yang dipahami dari pekataan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada Jabir Radhiyallahu ‘anhu (di saat ia tidak mampu melunasi hutang-hutang ayahnya yang wafat dalam keadaan meninggalkan hutang).
“Kalaulah telah datang harta (jizyah) dari Bahrain, niscaya aku memberimu sekian dan sekian” [Hadits Riwayat Al-Bukahri 2296 –Fathul Bari- dan Muslim 2314]
Dan jika negara atau pemerintah tidak menanggungnya, kemudian ada diantara kaum Muslimin yang siap menanggungnya, maka hal itu dibolehkan sebagaimana kandungan hadits Salamah bin Al-Akwa Radhiyallahu ‘anhu di atas. Hal itu memberi pelajaran bahwa mayit dapat memperoleh dengan dilunasinya hutang-hutangnya, meskipun oleh selain anaknya. Dengan demikian berarti akan membebaskannya dari adzab. [6]
Berbeda halnya dengan shadaqah, karena si mayit bisa memperoleh manfaat dan pahala dari shadaqah atas nama dirinya yang dilakukan oleh anaknya saja. Sebab anak merupakan hasil usaha orang tua, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta’ala.
“Dan bahwasanya, seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya” [An-Najm : 39]
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.
“Sesungguhnya, sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang ialah dari hasil usahanya sendiri. Dan anaknya, termasuk dari hasil usahanya” [Hadits Riwayat Abu Dawud 3528, An-Nasa’i 4449 dan 4451, At-Tirmidzi 1358 –dengan lafazh jamak- Ibnu Majah 2137. Dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahih Al-Jami 2208 dan tahqiq Misykatul Mashabih 2770] [7]
[3]. Jika hutang si mayit berkaitan dengan hak Allah seperti nadzar haji, maka wajib ditunaikan oleh si mayit dengan harta si mayit bila mencukupi. Sedangkan bila harta si mayit tidak mencukupi ketika wafatnya, maka ditanggung oleh walinya yang akan menghajikan untuk si mayit, sebagaimana kandungan dari hadits Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhu, bahwa pernah ada seorang wanita dari bani Juhainah datang kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan berkata :
“Sesungguhnya ibuku telah bernadzar haji, tetapi belum berhaji sampai meninggalnya, apakah aku harus menghajikan untuknya?” Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Ya, hajikanlah untuknya. Bukankah jika ibumu menanggung hutang maka kamu yang akan melunasinya? Tunaikanlah hak Allah, karena hak Allah lebih utama untuk ditunaikan” [Hadits Riwayat Al-Bukhari 1852- Fathul Bari]
[4]. Jika ia memiliki hutang yang berkaitan dengan hak Allah dan hak manusia, manakah yang lebih dahulu ditunaikan?
Dalam permasalahan ini, para ulama berbebda pendapat dalam tiga kelompok.[8]
Pertama : Harta si mayit yang ada dibagikan untuk hutang-hutang tersebut dengan masing-masing mendapat jatah bagian berdasarkan nisbah (prosentase), seperti pada kejadian seorang yang mengalami kebangkrutan, pailit (muflis), (yaitu) ketika dia menanggung hutang-hutang yang melampaui harta miliknya. Ini adalah pendapat ulama madzhab Hambali.
Kedua : Diutamakan hutang-hutang yang berkait dengan hak manusia, dengan mempertimbangkan oleh sifat asal manusia yang bakhil (tidak memaafkan). Adapun hak Allah dibangun atas dasar sifat Allah yang suka memaafkan. Ini adalah pendapat ulama madzhab Hanafi dan Maliki.
Ketiga : Yang benar adalah diutamakan hak Allah daripada hak manusia, berdasarkan keumuman hadits Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhu di atas, yaitu ketika Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.
“Tunaikan hak Allah, karena hak Allah lebih utama untuk ditunaikan” [Hadits Riwayat Al-Bukhari 1852 –Fathul Bari-] [9]
Pendapat ketiga ini merupan pendapat ulama madzhab Syafi’i. Wallahu a’lam
[Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi Khusus/Tahun IX/1426H/2005M. Penerbit Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Jl. Solo-Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo Solo 57183]
__________
Foote Note
[1]. Lihat Syarhu Shahih Muslim 11/33
[2]. Lihat juga Ahkamul Janaiz, hal. 25
[3]. Lihat Ahkamul Janaiz hal.25-26
[4]. Lihat Ahkamul Janaiz, hal. 25
[5]. Lihat Fathul Bari 4/558. Dan lihat perbedaan pendapat dalam masalah ini dalam Syarh Shahih Muslim 11/52
[6]. Lihat Ahkamul Janaiz, hal 28
[7]. Lihat Ahkamul Janaiz, hal.16
[8]. Lihat At-Tahqiqat Al-Mardhiyyah, hal.26
[9]. Lihat Nailul Authar 4/286-287
Sumber : http://www.almanhaj.or.id/content/2024/slash/0














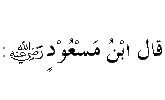




















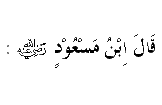














Comments (0)
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.