Oleh : Syaikh Ali bin Hasan al-Halabi Al-Atsari
PENGANTAR
Begitu indah aturan yang dihadirkan Islam bagi umat manusia. Semua sisi kehidupan dipenuhi dengan rambu-rambu yang tidak hanya sarat dengan kemaslahatan, tetapi juga membebaskan manusia dari bahaya. Bak santapan, maka kandungan Islam mengandung banyak nutrisi, hyginis atau bersih dari kotoran. Itulah substansi nilai-nilai Islam yang sangat kokoh melekat. Tulisan berikut ini menjelaskan beberapa hal berkaitan dengan keindahan kandungan syari’at Islam. Diadaptasi dari kitab Maqâshidusy-Syarî’ah ‘Inda Ibni Taimiyyah karya Dr. Yusuf bin Muhammad Al-Badawi, Darun- Nafâ-is, Yordania, Cetakan I, 1421 H / 2000 M. Kitab ini menjadi pegangan Syaikh Ali bin Hasan al-Halabi Al-Atsari pada Daurah Syar’iyyah I yang diselenggarakan oleh Yayasan Imam Bukhari, Jakarta, di Ciloto, Bogor, Jawa Barat, pada pertengahan bulan Februari 2007. Adapun penulisan makalah berikut ini dilakukan oleh Ustadz Ashim bin Musthafa yang meramunya dengan beberapa tambahan dari kitab lainnya. Semoga bermanfaat. (Redaksi).
AJARAN ISLAM MERUPAKAN KENIKMATAN MUTLAK
Tidak berlebihan, bila dikukuhkan bahwa kedatangan Islam sebagai kenikmatan yang mutlak, lantaran berhubungan erat dengan kebahagiaan abadi.
PENGANTAR
Begitu indah aturan yang dihadirkan Islam bagi umat manusia. Semua sisi kehidupan dipenuhi dengan rambu-rambu yang tidak hanya sarat dengan kemaslahatan, tetapi juga membebaskan manusia dari bahaya. Bak santapan, maka kandungan Islam mengandung banyak nutrisi, hyginis atau bersih dari kotoran. Itulah substansi nilai-nilai Islam yang sangat kokoh melekat. Tulisan berikut ini menjelaskan beberapa hal berkaitan dengan keindahan kandungan syari’at Islam. Diadaptasi dari kitab Maqâshidusy-Syarî’ah ‘Inda Ibni Taimiyyah karya Dr. Yusuf bin Muhammad Al-Badawi, Darun- Nafâ-is, Yordania, Cetakan I, 1421 H / 2000 M. Kitab ini menjadi pegangan Syaikh Ali bin Hasan al-Halabi Al-Atsari pada Daurah Syar’iyyah I yang diselenggarakan oleh Yayasan Imam Bukhari, Jakarta, di Ciloto, Bogor, Jawa Barat, pada pertengahan bulan Februari 2007. Adapun penulisan makalah berikut ini dilakukan oleh Ustadz Ashim bin Musthafa yang meramunya dengan beberapa tambahan dari kitab lainnya. Semoga bermanfaat. (Redaksi).
AJARAN ISLAM MERUPAKAN KENIKMATAN MUTLAK
Tidak berlebihan, bila dikukuhkan bahwa kedatangan Islam sebagai kenikmatan yang mutlak, lantaran berhubungan erat dengan kebahagiaan abadi.
“Dinul-Islam, benar-benar merupakan kenikmatan hakiki, yang pasti mengantarkan manusia kepada kehidupan yang kamâl (sempurna). Dan manusia sama sekali tidak bernilai, sebelum ia mengenal sesembahannya sesuai dengan tuntunan Islam, sebelum mengenal alam semesta ini sesuai dengan petunjuk Islam, sebelum memahami diri dan perannya di alam ini serta kemuliaannya di sisi Rabbnya sebagaimana dituturkan Islam yang telah diridhai Allah. Manusia tidak mempunyai harga apapun sebelum ia merdeka dari penyembahan terhadap sesama makhluk menuju peribadahan kepada Rabb semua makhluk. Tanpa nilai-nilai yang telah Allah anugerahkan melalui agama Islam yang lurus ini, manusia akan hidup layaknya binatang ternak yang berkeliaran, bahkan lebih sesat darinya, karena membalas nikmat Allah ini (berupa agama Islam) dengan kekufuran.
Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:
“Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami. Mereka itu tidak lain, hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya (dari binatang ternak itu)” [Al-Furqan : 43-44]
Bila memang sedemikian penting agama Islam ini, bahkan manfaatnya lebih dari apa yang dibayangkan oleh siapapun, maka ia benar-benar karunia paripurna yang semestinya membangkitkan kegembiraan. Kegembiraan terhadapnya termasuk perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Padahal, Allah tidak menyukai kaum farihin (bergembira).
Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman.
“(Katakanlah: “Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.) [Yunus : 58].”[1]
Senada dengan keterangan di atas, Sulthanul- ’Ulama, Al-’Izz bin ‘Abdis-Salamt rahimahullahu [2] berkata: “Maka, Allah Subhanahu wa Ta’ala mengenalkan kepada mereka segala hal yang mengandung petunjuk dan kemaslahatan bagi mereka, agar mereka mengerjakannya. Dan (Allah) mengenalkan setiap hal yang memuat kesesatan dan keburukankeburukan, sehingga mereka menghindarinya serta mengabarkan kepada mereka bahwa setan adalah musuh mereka, (dan) supaya mereka memusuhi dan menentangnya. Jadi, Allah Subhanahu wa Ta’ala menitikberatkan kemaslahatan-kemaslahatan dunia dan akhirat melalui ketaatan kepada-Nya dan menjauhi bermaksiat terhadap-Nya”[3]
MISI AJARAN ISLAM, JALBUL MASHALIH & DAR‘UL MAFASID
Di kalangan ulama, pembahasan mengenai tema misi ajaran Islam yang dibawa Rasulullahn, populer dengan istilah jalbul-mashâlih dan dar‘ul-mafasid.[4]
Mashalih jamak dari kata mashlahah yang bermakna kebaikan. Dan mafâsid jamak dari kata mafsadah yang diartikan oleh Ibnu Manzhur t dengan makna al-madharrah (bahaya) lawan dari ash- shalâh (kebaikan).
Al Ghazali rahimahullahu memaparkannya sebagai segala hal yang menghilangkan dharuriyyatulkhams.[5]
Pengertiannya secara global, yaitu mendatangkan seluruh kebaikan dan menghindarkan kerusakan-kerusakan. Tidak ada kebaikan bagi umat manusia, kecuali Islam telah menetapkan perintah dan anjuran padanya. Dan tiada keburukan ataupun kerusakan yang mengancam manusia, melainkan sudah ditetapkan peringatan dan larangan terhadapnya.
Misi di atas, merupakan misi seluruh para nabi yang diutus oleh Allah Ta’ala. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
“Sesungguhnnya tiada seorang nabi sebelumku, melainkan ia wajib menunjuki umatnya kepada kebaikan yang ia ketahui dan memperingatkan mereka dari keburukan yang ia ketahui untuk mereka". [HR Muslim]
Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman tentang peran Rasulullah Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam bagi sekalian alam
“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. [Al- Anbiya :107]
Terkadang, mashalih disebut dengan bahasa al-khair (kebaikan), an-naf’u (kemanfaatan) dan al-hasanaat (kebaikan-kebaikan). Sedangkan mafâsid, suatu waktu diungkapkan oleh syarî’at dengan bahasa asy-syarru (kejelekan), adh-dharru (bahaya) dan as-sayyi-ât (keburukan-keburukan).[6]
Demikian subtansi ajaran Islam, yaitu terletak pada dua point tersebut, yakni menghadirkan kebaikan-kebaikan dan melenyapkan keburukan-keburukan. Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullahu sering mengulang-ulang statemen ini di dalam kitab-kitab beliau. Misalnya, beliau mengatakan: “Aturan syari’at datang untuk menghasilkan kemaslahatan-kemaslahatan dan menyempurnakannya, dan meniadakan keburukan-keburukan dan menguranginya” [7]
Melalui telaah mendalam terhadap nash-nash syari’at dan pencermatannya yang tajam terhadap rahasia-rahasia di dalamnya, Syaikhul-Islam rahimahullahu menegaskan beberapa kaidah yang berhubungan dengan pembahasan ini. Di antaranya sebagai berikut.
[a]. Para rasul diutus ke dunia ini untuk mendatangkan kemaslahatan-kemaslahatan dan melengkapinya, dan meniadakan keburukan-keburukan dan menekan angkanya sesuai dengan kemampuan.[8]
[b]. Aturan syari’at memerintahkan perkara yang mengandung kebaikan yang murni atau lebih dominan, dan melarang dari perkara yang memuat kerusakan-kerusakan (keburukankeburukan) atau lebih dominan daripada muatan kebaikannya.[9]
Bahkan Sulthânul-’Ulama, Al-’Izz bin ‘Abdis- Salam menyimpulkan, fokus keberadaan syari’at ada pada satu titik saja, yaitu untuk menciptakan mashaalih semata bagi alam semesta. Kata beliau: “Semua aturan syari’at merupakan mashâlih. Baik untuk menolak keburukan maupun untuk mendatangkan kebaikan. Jika engkau mendengar Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman : “wahai orangorang yang beriman”, (maka) renungilah pesan- Nya setelah panggilan tersebut. Engkau tidak akan menemukan kecuali sebuah kebaikan yang dianjurkan Allah atas dirimu, atau keburukan yang Dia melarangmu darinya, atau berpaduan antara keduanya, anjuran dan larangan. Di sebagian ketetapan hukum dalam kitab-Nya, Allah menerangkan sejumlah keburukan agar dijauhi dan (menjelaskan) mashâlihnya sebagai himbauan supaya melakukan mashâlih”.[10]
Sudah jelas sekali, bagaimana perhatian Islam terhadap kebaikan umat manusia secara khusus, yang nantinya mengajak untuk meraih kebahagiaan hakiki, di dunia dan akhirat.
Al ‘Izz bin ‘Abdis Salam rahimahullahu menegaskan: “Semua kebahagiaan berpangkal dari mengikuti seluruh aturan syari’at yang datang, dan muncul disertai dengan menepis ajakan hawa nafsu yang menyelisihi syari’at. Allah Ta’ala Subhanahu wa Ta’ala berfirman: “(lalu barangsiapa yang mengikuti petunjuk-Ku, ia tidak akan sesat dan ia tidak akan celaka)” (Thaha ayat 123) maksudnya, ia tidak sesat di dunia dan tidak celaka di akhirat kelak dengan menerima siksa”[11]
Sebagai contoh, Islam memerintahkan manusia untuk beriman. Karena keimanan itu, sepenuhnya betul-betul bermanfaat. Islam menetapkan perintah berjihad yang mengandung kemaslahatan menyeluruh, walaupun menuntut pengorbanan jiwa. Akan tetapi, kemaslahatan jihad itu sendiri sangat kuat. Merebaknya kekufuran, dampaknya lebih berbahaya dibandingkan kematian di jalan Allah.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta’ala melarang perbuatan fawâhisy (kekejian), baik yang terlihat maupun tidak, melarang perbuatan dosa, kezhaliman tanpa kebenaran, perbuatan syirik terhadap Allah dengan segala sesuatu dan berdusta atas nama Allah l . Semua perkara tersebut adalah dilarang saat kapanpun dan dalam aturan syariat seluruh nabi.
Pengharaman darah, bangkai, babi dan lainnya yang sangat mengandung mafsadah, seperti pada khamr dan perjudian, meskipun ada manfaatnya bagi manusia, namun akibat dosanya lebih besar dibanding kemanfaatan yang bisa diraih. [12]
Oleh karena itu, benar-benar merupakan kekeliruan fatal jika seseorang memungkiri eksistensi mashâlih, mahâsin (sisi-sisi keindahan) dan maqâshid (orientasi) dalam syari’at yang telah ditetapkan Allah ini bagi umat manusia di dunia maupun akhirat. Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyyah menilai orang seperti itu dengan sebutan “orang yang telah mengalami kekeliruan, sesat. Kerusakan pernyataannya telah dimaklumi dengan mudah”.[13]
Begitu pula pendapat yang memandang bahwa kemaslahatan Islam hanya diperuntukkan di dunia ini saja, merupakan pendapat yang timpang, sebagaimana anggapan Ibnu Asyûr.[14]
[Disalin dari Majalah As-Sunnah Edisi 04/Tahun XI/1428H/2007M. Penerbit Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta]
__________
Foote Note
[1]. Ats Tsabât ‘Alal-Islam, Dârul-Minhaj, Kairo, Mesir, Tahun 1424 H – 2004 M, hlm. 14-15.
[2]. Imam ahli hadits, Sulthânul-’Ulama Abu Muhammad ‘Izzuddin ‘Abdul-’Aziz bin ‘Abdis-Salam bin Abil-Qasim bin Al-Hasan as- Sulami ad-Dimasyqi. Seorang ulama fiqih dari kalangan Syafi’iyyah. Lebih dikenal dengan panggilan Al-’Izz bin ‘Abdis-Salam. Lahir 577 atau 578 H, dan wafat 660 H.
[3]. Qawâ’idul-Ahkâm fî Mashâlihil-Anam, Al-’Izz bin ‘Abdis-Salam, Dârul-Bayanil-’Arabi, Tahun 1421 H – 2001 M, hlm. 5.
[4]. Untuk selanjutnya dalam pembahasan ini memakai dua ungkapan tersebut.
[5]. Lisânul-’Arab (5/3412), Al-Mushtashfa (2/481-482). Dinukil dari Maqâshidusy-Syarî’ah. Lihat Mabhats, Dharuriyatul-Khams.
[6]. Qawâ’idul-Ahkâm, hlm. 8.
[7]. Majmu’ AlFatâwa (1/265)
[8]. Majmu’ Al-Fatâwa (1/265, 10/512).
[9]. Majmu’ Al-Fatâwa (1/194, 11/331, 348).
[10]. Qawâ’idul-Ahkam, hlm. 11.
[11]. Qawâ’idu- Ahkam, hlm. 17.
[12]. Majmu’ Al-Fatâwa (27/230, 21/569, 1/265, 24/278-279), Al-Istiqâmah (1/153), Al-Maqâshid, hlm. 287.
[13]. Majmu’ Al-Fatâwa (11/179).
[14]. Maqâshidusy-Syari’ah, Ibnu ‘Asyûr, hlm. 13. Dikutip dari Al-Maqâshid, hlm. 285.
SEJAUH MANA AKAL MANUSIA DAPAT MENGETAHUI KEBAIKAN DAN KEBURUKAN?
Tingkat kemampuan akal antara seseorang dengan orang lainnya sangat variatif. Kebenaran, penilaian baik dan buruk, bila hanya didasarkan pada kecerdasan akal manusia belaka, sungguh sangat naif. Karena ia bersifat nisbi dan relatif. Bukti kongkretnya, aturan-aturan produk manusia seringkali mengalami perubahan dan revisi seiring dengan perkembangan zaman dan perbedaan pemegang kendalinya.
Sehingga, penilaian baik oleh seseorang tidak menutup kemungkinan disanggah oleh orang lain. Akibatnya terjadi khilaf dalam menilai baik atau buruk terhadap sebuah obyek atau perilaku. Tidak mungkin perbedaan pandangan ini diselesaikan, kecuali dengan kembali kepada sumber yang tidak diperselisihkan statusnya. Yakni, kembali kepada Al-Kitab dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman.
“Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” [An-Nisâ: 59] [15]
Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu bahwa orientasi syari’at Islam ialah untuk menciptakan segala bentuk mashlahah. Dengan begitu, tidak ada satu pun kemashlahatan yang terbengkalai dalam pandangan syari’at. Allah Subhanahu wa Ta’ala telah menyempurnakan agama Islam bagi kaum Muslimin dan menyempurnakan kenikmatan bagi mereka.
Ibnul-Qayyim rahimahullahu memperjelas kenyataaan bahwasanya Allah Ta’ala telah menanamkan pada fitrah manusia yang masih bersih dan akal, yaitu berupa kemampuan untuk menilai baik terhadap kejujuran, berbuat baik kepada orang lain, ‘iffah, sifat ksatria, akhlak yang luhur, amanah, silaturrahmi, menepati janji... dan menilai buruk terhadap tindak-tanduk yang berlawanan dengan fitrah tersebut. Akan tetapi, kemampuan akal dan fitrah manusia dalam konteks tersebut, hanya bagaikan hasratnya terhadap air sejuk saat dahaga, makanan yang lezat ketika merasa lapar dan keinginan mengenakan pakaian hangat ketika kedinginan. Jalan yang paling benar dari cara di atas, yaitu melalui as-sam’u (wahyu), karena adanya kekaburan yang dialami akal dan fitrah dalam memahami sebagian hakikat persoalan. Adapun orang yang mengetahui secara terperinci tentang itu ialah Rasulullahn Shallallahu ‘alaihi wa sallam. [16]
Oleh sebab itu, keberadaan syari’at Islam yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta’ala di tengah manusia adalah mutlak. Sebab, akal, bagaimanapun canggihnya, ia tidak mampu meneropong segala kebaikan dan keburukan yang hakiki. Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullahu menyatakan: “Seandainya tidak ada risalah, akal manusia tidak mampu mengetahui aspek-aspek yang bermanfaat dan berbahaya di dunia dan di akhirat secara terperinci”. [17]
Beliau menambahkan: “Sudah menjadi kewajiban atas setiap orang untuk mengerahkan kemampuan dan kesanggupannya supaya mengetahui kandungan risalah yang dibawa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan taat kepada beliau. Dan caranya, yaitu melalui ar-riwâyah (periwayatan) dan nukilan an-naql (wahyu). Karena, akal semata tidak mampu untuk itu. Sebagaimana cahaya tidak dapat melihat, kecuali dengan keberadaan cahaya di depannya. Begitu pula akal manusia tidak kuasa mencari hidayah, kecuali ketika pancaran risalah tersebut terbit”[18]
Sulthânul-’Ulama Al ‘Izz bin ‘Abdis-Salam rahimahullahu juga menuturkan keterangan yang sama. Kata beliau: “Adapun mashâlih dan mafâsid dunia akhirat dan faktor-faktor penyebabnya tidak dapat diketahui, kecuali dengan syari’at. Bila ada yang masih belum jelas, maka dicari melalui dalil-dalil syari’at, yaitu Al-Kitab, as-Sunnnah, Ijma’, Qiyas yang mu’tabar, serta istidlâl yang shahîh”[19]
Dalam persoalan ini, terdapat pula penyimpangan dari sejumlah aliran. Para pengusungnya telah disinggung oleh Syaikhul- Islam Ibnu Taimiyyah, sebagai berikut.[20]
Pertama, adalah sekte Mu’tazilah Qadariyyah, sebagian ulama Syafi’iyyah dan banyak kalangan dari ulama Hanafiyyah.
Mereka menyatakan, pada dasarnya obyek yang diperintahkan atau dilarang tersebut memang baik maupun buruk, sebelum munculnya ketetapan tersebut. Ketetapan perintah dan larangan hanya sekedar menyibak karakteristik yang menyatu dengannya, tidak mengakibatkan penilaian baik atau buruk. Menurut pandangan mereka, tidak boleh memunculkan penetapan perintah atau larangan atas dorongan hikmah yang timbul dari perkara itu sendiri.
Lain lagi dengan ideologi yang bersumber dari aliran Jahmiyyah Jabriyyah dan kalangan Asy’ariyyah. Mereka memandang, sebuah perintah tidak memuat hikmah apapun, baik dari perintah itu sendiri atau implikasinya. Allah Subhanahu wa Ta’ala tidak menciptakan apapun atas dasar hikmah. Kehendak Allah-lah yang menentukan kemunculan apa yang sudah ada, dan penentuan salah satu dari dua hal yang serupa tanpa faktor khusus. Kebaikan maupun keburukan menurut persepsi mereka, bukanlah bagian dari sifat yang menyatu pada sebuah obyek. Kebaikan dan keburukan itu, tidak lain lantaran telah dinilai baik atau buruk oleh syari’at. Secara implisit maupun eksplisit, tidak ada unsur kebaikan maupun keburukan berkaitan dengan obyek tersebut. Pada gilirannya, konsekuensi dari pandangan mereka, maka Allah Subhanahu wa Ta’ala boleh memerintahkan sebuah perintah, sekalipun berujud kekufuran, perbuatan fasik maupun maksiat. Begitupun, melarang segala perkara, kendatipun masalah tauhîd, kejujuran ataupun keadilan.
Dua pandangan di atas sangat bertentangan dengan orientasi syari’at Islam, yang memberikan kebaikan sebesar-besarnya bagi alam semesta. Pandangan ini juga menyelisihi pandangan para sahabat Rasulullah dan generasi selanjutnya yang mengikuti mereka dengan setia.
Dalam pandangan mereka, hikmah yang timbul bervariasi menjadi tiga macam.
Tindakan tersebut mengandung unsur maslahat atau mafsadah, meskipun syari’at belum menyinggungnya. Misalnya, sudah diketahui bersama bahwa kejujuran mengandung kemaslahatan, dan kezhaliman menimbulkan mafsadah. Dua hal itu sudah masuk dalam kategori hasan (baik) atau qabîh (buruk), yang bisa dicerna oleh akal dan melalui syari’at. Bukan atas dasar sifat yang sebelumnya tidak melekat padanya. Akan tetapi, hal ini tidak otomatis menyebabkan pelakunya harus menerima hukuman di akhirat kelak, bila syari’at belum menetapkannya. Inilah di antara kesalahan kalangan yang ekstrim dalam berasumsi kebaikan dan keburukan bisa diambil melalui akal semata. Mereka menyatakan, bahwa orang-orang akan disiksa atas perilaku mereka yang buruk, meskipun Allah belum mengutus seorang rasul yang menjelaskan sisi keburukannya kepada mereka. Amat jelas, kalau pemahaman ini bertentangan dengan ayat:
“Dan Kami tidak akan mengadzab sebelum Kami mengutus seorang rasul” [Al-Isra :15]
“(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” [An-Nisa 165].
Kedua : Sesungguhnya perkara yang diperintahkan dan dikenakan larangan, menjadi obyek yang memperoleh sifat kebaikan lantaran syari’at memerintahkannya atau ternodai oleh keburukan akibat pelarangannya. Sebagai contoh, khamr (minuman keras, minuman yang memabukkan), yang sebelumnya bukan barang haram, kemudian datang ketetapan yang mengharamkannya, sehingga khamr beralih menjadi barang khabîtsah (keji).
Jenis Ketiga : Yakni adanya hikmah dengan adanya perintah tersebut, tetapi bukan sebuah maslahat. Orientasinya hanyalah sebagai ujian bagi seorang hamba, apakah menjadi manusia yang taat atau sebaliknya justru melanggar aturan tersebut. Sebagaimana dialami oleh Al-Khalîl yang diperintahkan untuk menyembelih anaknya, Ismail.
Bentuk ketiga inilah yang kabur, belum bisa dicerna oleh kalangan Mu’tazilah. Persepsi mereka, kebaikan dan keburukan itu tidak muncul kecuali sebagai sifat yang menyatu dengan sesuatu, tanpa ketetapan dari syari’at. Sedangkan golongan Asy’ariyyah berpandangan, segala aturan syari’at hanya ditujukan sebagai imtihân (ujian) belaka, dan seluruh tindak-tanduk tidak mempunyai implikasi apapun, baik sebelum ditetapkan oleh syari’at sebagai larangan dan perintah, maupun setelah ditetapkan. Hikmah ditetapkannya syari’at tidak pernah mereka perhatikan, baik dalam hal perintah maupun larangan. Adapun para orang bijak, mayoritas ulama, mereka menetapkan tiga jenis ini, dan itulah pendapat yang benar dan menandakan kecerdasan jiwa.[21]
Jadi, berdasarkan keterangan Ibnu Taimiyyah, bahwa akal dan fitrah kadang bisa mandiri dalam menentukan sisi kebaikan atau keburukan sesuatu, akan tetapi sangat terbatas. Selain itu, pengetahuan akal tentang baik buruknya suatu perkara tidak berdampak pada balasan akhirat, berupa pahala, siksa, selama tidak ada dalil yang menetapkannya.[22]
Pandangan Ibnu Taimiyyah itu dalam perkaraperkara yang berhubungan dengan budaya dan pengalaman-pengalaman. Adapun yang berhubungan dengan ibadah, seperti shalat, thawaf dan lain-lain, sesungguhnya akal tidak memiliki andil sedikit pun.[23]
Ibnul-Qayyim rahimahullahu juga menandaskan: Pernyataan yang menentukan permasalahan ini, bahwasanya aspek kebaikan dan keburukan, kadang termuat pada suatu tindakan tertentu, akan tetapi Allah tidak menetapkan pahala atas pelaksanaannya, dan tidak menghukumi karenanya melainkan setelah ditegakkan hujjah dengan mengirimkan rasul. Inilah permasalahan yang tidak diperhatikan oleh golongan Mu’tazilah.[24]
Ringkasnya, syari’at tidak pernah mengesampingkan kemaslahatan terhadap sesuatu apapun, bahkan Allah l telah menyempurnakan agama Islam dan menyempurnakan kenikmatan bagi kaum Muslimin. Namun, apabila akal meyakini adanya kemaslahatan pada suatu perkara yang ternyata belum ditetapkan oleh syari’at, maka tidak terlepas dari dua kemungkinan. Pertama, sebenarnya syari’at telah menunjukkannya, tetapi belum terlihat oleh manusia. Atau sebetulnya perkara tadi bukan sebuah kemaslahatan, kendati diyakini oleh akal sebagai kemaslahatan. Karena yang dinamakan mashlahah, ialah kemaslahatan yang murni atau yang dominan. [25]
PENUTUP
Secara keseluruhan, agama Islam mengandung kemaslahatan. Ibnul Qayyim rahimahullahu mengatakan: “Jika engkau merenungi hikmah dalam agama yang lurus ini, ajaran yang hanif dan syari’at yang diemban Rasulullah Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam, yang kesempurnaannya tidak bisa disampaikan melalui ungkapan, imajinasi pun tidak mampu membayangkan keindahannya, dan daya pikir para cendikiawan tidak mampu menggagas ajaran yang lebih baik darinya, kendatipun mereka bersatu dengan bantuan daya pikir yang paling cerdas. Cukuplah menjadi kebaikan Islam, bahwa akal-akal yang sempurna lagi utama telah mengetahui keelokannya dan mengakui keutamaannya. Dan sesungguhnya tidak pernah ada ajaran di alam dunia ini yang lebih sempurna, lebih agung dan besar daripadanya. Seandainya Rasulullah tidak membawa bukti atas kebenarannya, cukuplah syari’at itu sebagai petunjuk yang membuktikannya”.[26]
Karenanya, umat manusia benar-benar membutuhkan syari’at Islam, lantaran mengandung seluruh kemaslahatan yang besar, mempedulikan mashâlih manusia di dunia maupun di akhirat dan menjadi sarana untuk menggapai keselamatan dan kebahagiaan. Allah menjelaskan dalam kitab-Nya, bahwa syari’at- Nya merupakan shirâthul-mustaqim (jalan yang lurus), jalan yang lurus dan metode yang benar. Siapa saja yang konsisten di atasnya, niscaya akan selamat. Dan barang siapa yang berpaling, maka akan binasa”[27]
Oleh sebab itu, seperti diungkapkan oleh Syaikh Abdur-Razzaq Al-’Abbad dalam Asbabul Ziyadatul-Iman wa Nuqshanihi [28] (hlm. 36), bahwa merenungi sisi-sisi keindahan Islam dan kandungan risalah Islam yang memuat berbagai perintah, larangan, aturan, hukum, akhlaq dan etika, termasuk merupakan faktor penting yang menjadi daya tarik orang untuk masuk Islam, dan pertambahan keimanan bagi para pemeluknya. Wallahul-muwaffiq.
__________
Foote Note
[15]. Raf’udz-Dzulli wash-Shaghâr ‘anil-Maftunîn bi Khuluqil-Kuffar, ‘Abdul-Malik bin Ahmad Ramdhani, Cetakan II, Tahun 1426 H, hlm. 52.
[16]. Ighatsatul-Lahafan (2/138). Dinukil dari Raf’udz-Dzulli, hlm. 52-53.
[17]. Majmu Al-Fatâwa (19/99-100).
[18]. Majmu Al-Fatâwa (1/5-6, 3/338-339).
[19]. Qawâ’idul-Ahkam, hlm. 11.
[20]. Minhajus-Sunnah (3/14), Majmu Al-Fatâwa (8/90, 341, 17/198), Syarhul-Ashfahaniyyah, hlm. 161.
[21]. Majmu Al-Fatâwa (8/431-436, 17/198-203, 11/347, 354).
[22]. Maqâshidusy-Syari’ah ‘inda Ibni Taimiyyah, hlm. 294.
[23]. Maqâshidusy-Syari’ah ‘Inda Ibni Taimiyyah, hlm. 294-295.
[24]. Miftahu Dâris-Sa’adah hlm. 333-334, 367, 372, 374-355.
[25]. Majmu Al-Fatâwa (11/344-345), Maqâshidusy-Syari’ah ‘Inda, 295.
[26]. Miftahu Dâris-Sa’adah, hlm. 324. Dinukil dari Asbabu Ziyadatil-Îman wa Nuqshanini, hlm. 36.
[27]. Asyari’atul-Islamiyyah wa Mahâsinuha wa Dharûratil-Basyari Ila-iha, Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin Baz, hlm. 50.
[28]. Diterbitkan Dâr Ghirâs, Cetakan III, Tahun 1424 H – 2003 M.
[Disalin dari Majalah As-Sunnah Edisi 04/Tahun XI/1428H/2007M. Penerbit Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta]
Sumber : http://www.almanhaj.or.id/content/2202/slash/0














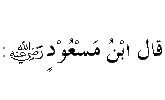




















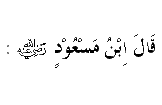














thanks gan, atas infonya