Pendahuluan
Setiap (kelompok) yang menyimpang dari Sunnah namun mendakwahkan dirinya menerapkan Sunnah, mesti akan takalluf (memaksakan diri) mencari-cari dalil untuk membenarkan tindakannya (penyimpangan) mereka. Karena, kalau hal itu tidak mereka lakukan, (perbuatan mereka) mengesampingkan Sunnah itu sendiri telah membantah dakwaan mereka.
Setiap pelaku bid’ah dari kalangan umat Islam ini mengaku bahwa dirinya adalah pengikut Sunnah -berbeda dengan firqah-firqah lain yang menyelisihinya- hanya saja mereka belum sampai kepada derajat memahami tentang Sunnah secara utuh. Hal itu mungkin karena tidak dalamnya pemahaman mereka tentang perkataan bahasa arab dan kurang paham maksud-maksud yang dikandung Sunnah. Atau, mungkin juga karena tidak dalamnya pemahaman mereka dalam hal pengetahuan kaidah-kaidah ushul sebagai landasan ditetapkannya hukum-hukum syari’at, atau mungkin pula karena dua hal tersebut sekaligus.
Tentang golongan kedua, yaitu tidak dalam pengetahuannya tentang kaidah-kaidah ushul , yang condong dan menyimpang dari kebenaran, kita mendapatkan dua sifat pada mereka berdasarkan ayat Al-Qur’an.
Sifat Pertama, yaitu sifat condong dan menyimpang, yaitu pada firman Allah Ta’ala:
“Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kecondongan (dari kebenaran).” [Ali Imran : 7]
Condong dalam ayat di atas maknanya adalah menyimpang dari jalan yang lurus; dan hal itu merupakan bentuk celaan terhadap mereka.
Sifat Kedua, tidak mendalamnya ilmu mereka (tentang kaidah-kaidah ushul). Menurutmu, bagaimana jadinya bila dia mengikuti (suatu dalil) hanya karena ingin mencari fitnah? Kita sering melihat orang-orang bodoh berhujjah untuk (membela) diri mereka dengan dalil-dalil yang batil; atau dalil-dalil yang shahih, (tapi hanya sepotong-sepotong); sebagian dalil dilirik dan dalil-dalil yang lain dibuang, baik dalam urusan pokok maupun cabang, baik yang mendukung pendapatnya ataupun yang bertentangan dengannya.
Banyak di antara mereka yang mengaku memiliki ilmu, ternyata mengambil cara ini sebagai jalannya. Dia pun mungkin saja memberikan fatwa sesuai dengan yang dikehendaki dalil dan mengamalkan apa yang telah difatwakannya itu dan tujuan (tertentu). Cara seperti ini bukan merupakan kebiasaan orang-orang yang mendalam ilmunya. Cara itu tidak lain merupakan kebiasaan orang-orang yang tergesa-gesa, yang menurut dakwaannya hal itu adalah menjadi solusi.
Dari ayat yang telah disebutkan di muka kita dapatkan bahwa sifat menyimpang dari kebenaran tidak akan terjadi pada seorang yang mendalam ilmunya. Walaupun tidak semuanya begitu, akan tetapi seseorang yang mendalam ilmunya tidak akan menyimpang dari kebenaran dengan sengaja.
Jalan Yang ditempuh Orang Yang Menyimpang
Sesungguhnya orang yang mendalam ilmunya memiliki jalan yang mereka tempuh dalam mengikuti kebenaran, dan orang-orang yang menyimpang mempunyai jalan lain yang berbeda.
Kita perlu mengetahui jalan-jalan yang ditempuh oleh mereka (orang-orang yang menyimpang) untuk kita jauhi. Mari kita perhatikan sebuah ayat yang menyebutkan bagaimana jalan mereka dan bagaimana jalan orang-orang yang mendalam ilmunya. Allah Ta’ala berfirman:
“Dan sesungguhnya ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lainnya karena itu akan mencerai Beraikan kalian dari jalan-Nya.” [Al-An’am: 153]
Ayat di atas menyebutkan bahwa jalan kebenaran hanyalah satu, sedangkan kebatilan memiliki jalan-jalan yang banyak; tidak hanya satu, dan tidak terbatas jumlahnya.
Kemudian mari kita perhatikan pula sebuah hadist yang menafsirkan ayat tersebut yang diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud Radhiyallahu 'anhu.
“(Suatu Ketika) di hadapan kami Rasulullah menggambarkan satu garis,lalu berkata, ‘Ini adalah jalan Allah yang lurus.” Kemudian beliau menggambarkan garis-garis lain yang banyak di kanan dan kiri garis tadi, lalu berkata, ‘Ini adalah jalan-jalan lain (selain jalan Allah), yang pada setiap jalan tersebut ada syaitan yang mengajak kepadanya.” Kemudian beliau membacakan ayat ini.” [Hadist Shahih]
Dalam hadist di atas disebutkan adanya garis(maksudnya kelompok-kelompok sesat) yang banyak, beragam dan tidak terbatas jumlahnya. Secara naqli kita tidak boleh membatasi jumlahnya; begitu juga secara aqli ataupun istiqra’ (penelitian). Akan tetapi akan kita sebutkan beberapa patokan secara umum untuk dijadikan pedoman melihat kelompok-kelompok tersebut, yaitu:
[1]. Mereka Bersandar Kepada Hadist-Hadist Lemah
Hadist-hadist yang lemah sandnya besar kemungkinan tidak diucapkan pleh Nabi. Jadi tidak mungkin suatu hukum didasarkan kepada hadist-hadist seperti itu. Bagaimana bila hadist-hadist yang mereka jadikan hujjah telah dikenal dusta?
[2]. Mereka Menolak Hadist-Hadist (Shahih), Yang Tidak Sejalan Dengan Tujuan Dan Madzhab Mereka.
Mereka mengatakan bahwa (hadist-hadist) seperti itu menyelisihi akal, tidak mengacu kepada maksud suatu dalil, maka harus ditolak. Dengan berdalih seperti itu mereka mengingkari siksa kubur, ash-shirath (jembatan), mizan (timbangan amal), dan ru’yatullah (melihat Allah) di akhirat nanti. Mereka juga menolak hadist tentang ‘lalat’ dan (perintah untuk) membunuhnya (yaitu dengan membenamkan ke dalam minuman yang dimasukinya. pent). Mereka tidak mempercayai bahwa pada salah satu sayap lalat terkandung penyakit sedangkan pada sayap satunya terkandung obat penawarnya, dimana Rasulullah lebih dahulu menyebutkan sisi sayap yang terkandung penyakit (Lihat Kitab Shahih Bukhari (Hadist no.3142) dan kitab lainnya. Pent). Dan masih banyak hadist-hadist shahih lainnya (yang mereka tolak) yang diriwayatkan oleh orang-orang yang adil (terpercaya). Bahkan, mereka mencela para periwayat hadist-hadist tersebut, dari kalangan sahabat maupun tabi’in sekalipun; dan juga mencela orang-orang yang telah disepakati keadilan dan keimanan mereka oleh para muhadditsin (ahli hadist). Semua itu mereka lakukan untuk membantah siapa saja yang menyelisihi madzhab mereka. Mereka menolak fatwa-fatwa dari orang-orang yang menyelisihi mereka dan menjelek-jelekannya dihadapan khalayak manusia, untuk menjauhi umat Islam dari Sunnah dan orang-orang yang mengikutinya.
[3]. Mereka Menerka-Nerka Maksud Perkataan Yang Ada Dalam Al-Qur’an Dan Sunnah Yang Berbahasa Arab.
Mereka menerka-nerka maksud perkataan yang ada dalam Al-Qur’an dan Sunnah yang berbahasa Arab, padahal mereka tidak memiliki ilmu bahasa Arab yang cukup untuk memahami apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya itu. Akhirnya mereka membuat kebatilan terhadap syari’at dengan pemahaman dan cara mereka, menyelisihi orang-orang yang mendalam ilmunya. Dan mereka lakukan hal itu tidak lain karena berprasangka baik terhadap diri mereka sendiri dan berkeyakinan bahwa mereka termasuk golongan ahli ijtihad yang berhak menetapkan hukum, padahal realitanya mereka bukan termasuk golongan tersebut.
[4]. Mereka Menyeleweng Dari Prinsip-Prinsip Agama Yang Telah Jelas Dan Mengikuti Perkara-Perkara Yang Samar (Mutasyabihat) Yang Mungkin Diperselisihkan Oleh Akal Masing-Masing Orang
Para ulama telah menetapkan bahwa setiap dalil yang didalamnya mengandung kesamaran dan kesulitan, pada hakekatnya bukanlah dalil, sampai menjadi jelas maknanya dan terang apa yang dimaksud. Karena hakekat sebuah dalil adalah keadaan dzanya sendiri harus jelas dan bisa (secara jelas pula) menunjukkan kepada sesuatu yang lain. Jika tidak demikian berarti masih membutuhkan dalil lagi. Lalu jika dalil tersebut menunjukkan akan ketidak shahihannya (sebagai Sebuah Dalil) berarti tidak layak untuk dikatakan sebagai dalil.
Sumber kekeliruan mereka dalam hal ini tidak lain adalah kebodohan mereka tentang maksud-maksud syari’at dan tidak mau memadukan dalil-dalil syar’I satu dengan lainnya. Kerena menurut orang-orang yang mendalam ilmunya, dalam mengambil dalil-dalil syar’i haruslah secara utuh dan memenuhi kaidah-kaidah syar’i, misalnya.
[a]. Suatu unsur merupakan juz’iyyat (bagian) dari suatu kulliyat (kumpulan besar);
[b]. Sesuatu yang ‘am (umum) biasanya diikuti dengan sesuatu yang khas (khusus);
[c]. Sesuatu yang muthlaq (mutlak) biasanya diikuti dengan muqayyid (yang membatasi);
[d]. Sesuatu yang mujmal (global) biasanya diikuti dengan bayan (penjelas);
[e]. Dan lain-lain yang serupa dengan itu.
[5]. Menyimpangkan Dalil-Dalil Dari Arti Yang Sebenarnya
Bila ada dalil yang membahas perkara tertentu, (mereka) palingkan dari perkara tersebut kepada perkara lain dengan anggapan bahwa dua perkara itu sama. Inilah di antara bentuk penyimpangan tersembunyi yang mereka lakukan terhadap dalil-dalil dari makna yang sebenarnya. Semoga Allah Ta’ala melindungi kita dari perbuatan demikian.
Besar kemungkinan, orang yang mengakui Islam dan mengetahui tercelanya tindakan menyimpangkan kata-kata dari makna sebenarnya itu, tidak akan melakukan penyimpangan semacam itu. Akan tetapi mereka mungkin melakukan hal itu tatkala ada kesamaran yang melintas pada dirinya, atau karena kebodohan yang menghalangi dirinya untuk mengetahui kebenaran, bahkan adakalanya disertai hawa nafsu yang membutakan hatinya untuk mengambil dalil dari sumbernya. Nah, bila sebab-sebab tersebut terkumpul jadilah dia seorang pelaku bid’ah.
Penjelasannya sebagai berikut. Dalil syar’i yang mengandung suatu perintah global dalam urusan peribadatan, seperti: berdzikir, berdo’a, amalan-amalan sunnah yang dianjurkan, dan amalan-amalan lainnya yang pelaksanaannya tidak diatur tatacara pelaksanaannya oleh Allah Ta’ala, maka harus dilakukan oleh seorang mukallaf secara global juga. Jadi dalil tersebut harus dia pahami dari dua sisi: (yaitu) sisi maknanya dan bagaimana para Salafus salih mengamalkan dalil tersebut. Jiak seorang mukallaf mengerjakan perintah tersebut dengan tata cara tertentu, atau di waktu tertentu, dan dia konsisten melakukan itu sehingga dia menganggap bahwa tata cara, atau waktu, atau tempat tersebut adalah yang dimaksudkan oleh syari’at dengan tanpa dalil yang menunjukkan kepada hal itu, maka dalil yang global tersebut telah dia lepas dari makna seharusnya.
Untuk memperjelas kita berikan gambaran demikian. Kita tahu, bahwa syari’at menganjurkan kita berdzikir kepada Allah Ta’ala. Lalu ada suatu kaum yang (senantiasa melakukannya) dengan cara berjama’ah secara serempak dengan satu suara, atau pada waktu tertentu, dengan dikomandoi oleg seorang seperti yang biasa terjadi di masjid-masjid, padahal kita tahu syari’at tidak menganjurkan yang seperti itu, bahkan justeru sebaliknya. Maka, perbuatan seperti itu jelas menyelisihi kaidah. Karena, pertama, dia telah meyelisihi kemutlakan suatu dalil dengan memberi batasan-batasan tertentu sekehendak akalnya; dan kedua, dia menyelisihi orang-orang yang lebih paham tentang syari’at daripada dirinya, yaitu para Salafus shalih. Padahal Rasulullah sendiri pernah meninggalkan suatu amalan –padahal beliau senang melakukannya- karena khawatir hal itu akan diikuti oleh manusia yang kemudian diwajibkan kepada mereka. Bukankah kita mengetahui, bahwa yang senantiasa Rasulullah lakukan secara jama’ah, bila bukan shalat fardhu berarti shalat sunnah muakkad, menurut para ulama, seperti dua shalat Id, yaitu Idul Fitri dan Idul adh-ha, shalat Istisqa’ (minta hujan), shalat kusuf (gerhana matahari), atau semisalnya? Beliau tidak melakukannya secara berjama’ah untuk shalat malam dan perbuatan-perbuatan sunnah lainnya, karena shalat-shalat tersebut hanya mustahab (yang dianjurkan) saja hukumnya. Rasulullah sendiri menganjurkan kita melaksanakan shalat-shalat tersebut secara sendiri-sendiri. Hal itu tidak lain karena bisa menyusahkan bila shalat-shalat tersebut pelaksanaannya ditunjukkan dan dinampakkan (dengan berjama’ah).
Contoh kasus lain dalam hal ini adalah membiasakan berdo’a setelah sholat dengan cara bersama-sama dan mengeraskannya. Masalah ini akan dibahas secara khusus di bagian belakang Insya Allah Ta’ala.
[6]. Ada Diantara Mereka Yang Menetapkan Perkara-Perkara Syar’i Berdasarkan Takwil Yang Tidak Bisa Diterima Akal.
Mereka mendakwakan (hasil penetapannya itu) bahwa itulah yang dimaksud dan yang diinginkan oleh syari’at. Sementara mereka tidak (memahami dalil-dalil syar’I) seperti yang dipahami oleh orang Arab. Mereka berkata: “Setiap apa yang terdapat dalam syari’at, baik menyangkut hal-hal yang harus dilakukan oleh manusia, masalah dikumpulkannya manusia dan membeberkannya amalan-amalan mereka (pada hari kiamat), serta perkara-perkara yang terkait dengan penyembahan (kepada Allah), maka itu adalah contoh-contoh urusan yang ghaib.”
[7]. Berlebihan Dalam Mengangungkan Guru-Guru Mereka
Mereka mendudukkan guru-guru mereka itu pada tempat yang tidak selayaknya. Kalau tidak karena berlebih-lebihan dalam beragama, berlebihan membela madzhab, dan berlebihan dalam mencintai pelaku bid’ah, tentu tidak akan ada pada pikiran seseorang untuk mengagungkan guru seperti itu. Akan tetapi Rasulullah telah bersabda.
"Sungguh kalian akan mengikuti jalannya orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, dan sehasta demi sehasta" [HR.Bukhari no. 3456 dan Muslim no. 2669 dan yang lainnya dari hadist Abu Sa’id Al-Khudri]
Jadi, mereka itu berlebih-lebihan (terhadap guru-guru mereka) seperti halnya orang-orang Nasrani berlebih-lebihan terhadap ‘Isa bin Maryam, yang berkata, “Sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih Ibnu Maryam". Maka, Allah berfirman:
"Katakanlah (Wahai Muhammad), ”Wahai Ahli Kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian dengan cara yang tidak benar. Dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sejak dahulu telah sesat (sebelum kedatangan Muhammad) ; dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia) dan mereka pun tersesat dari jalan yang lurus" [Al-Ma’idah : 77]
Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:
“Janganlah kalian berlebih-lebihan (memuji)ku, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan (memuji) ‘Isa Putera Maryam, tetapi katakanlah : (Aku ini) Hamba Allah dan Rasul-Nya". [HR. Bukhari no. 6830 dari Umar bin Al-Khathab]
Barangsiapa memperhatikan orang-orang (yang melakukan tindakan seperti di atas) niscaya akan menemukan banyak perbuatan bid’ah yang mereka lakukan dalam cabang-cabang syari’at. Karena, memang, yang namanya Bid’ah bila telah masuk ke dalam perkara pokok (ushul), maka akan mudah masuk kedalam cabang-cabangnya (furu’).
[8]. Berhujjah Dengan Mimpi-Mimpi
Hujjah yang paling lemah adalah hujjah suatu kaum yang menyandarkan kepada mimpi-mimpi untuk melaksanakan atau meninggalkan suatu amalan. Mereka biasanya berkata, “Kami bermimpi bertemu dengan si fulan, -biasanya seseorang yang shalih-, lalu dia berkata kepada kami, ‘Tinggalkan amalan itu, dan lakukan amalan ini!” Sebagian yang lain berkata, “Aku bermimpi (berjumpa) Rasulullah di waktu tidur, lalu beliau berkata begini dan memerintahkan begitu,”kemudian mengamalkan atau meninggalkan suatu amalan berdasarkan mimpinya itu, berpaling dari batasan-batasan yang telah dibuat oleh syari’at.”
Jelas itu suatu kesalahan. Karena, menurut syari’at, selain mimpi para nabi sama sekali tidak bisa diambil sebagai hukum. Mimpi-mimpi tersebut harus dikembalikan kepada hukum-hukum syari’at yang ada. Kalau cocok dengan hukum syari’at, maka mimpi tersebut boleh diamalkan, namun bila tidak cocok, maka wajib ditinggalkan dan dijauhi. Mimpi bisa kita jadikan sebagai kabar gembira atau peringatan saja ; tidak bisa dijadikan ketetapan hukum. Dan tidak bisa kita berkata, “Mimpi adalah satu bagian dari kenabian yang tidak boleh diabaikan. Bisa jadi yang mengabarkan dalam mimpi itu adalah Rasulullah, karena beliau bersabda:
"Barangsiapa melihatku di waktu tidur maka dia benar-benar telah melihatku, karena syetan tidak dapat menyerupaiku.” [Diriwayatkan oleh Al-Bukhari no. 6993, Muslim no. 2266 dari Abu Hurairah. Diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari no. 6994 dari Anas no. 6997 dan dari Abu Said Al-Khudri ; serta Muslim no. 2268 dari Jabir]
Jadi pengabaran beliau pada saat tidur (mimpi) sama seperti pengabaran beliau pada saat terjaga.
(Tidak bisa kita berkata seperti perkataan di atas), karena:
[1]. Jika mimpi adalah salah satu bagian dari kenabian, maka mimpi tersebut bukan merupakan wahyu secara keseluruhan, melainkan hanya sebagiannya saja. Sedangkan satu bagian itu tidak bisa menduduki tempat secara keseluruhan dalam segala sisi, melainkan hanya mendudukinya pada beberapa sisi saja. Mimpi bisa dipakai sebagai bentuk kabar gembira (bisyarah) dan peringatan (nidzarah) saja, tidak menjangkau aspek hukum.
[2]. Mimpi merupakan bagian dari kenabian di antara syaratnya adalah harus merupakan mimpi yang benar dari seorang yang shalih. Padahal terpenuhinya syarat-syarat tersebut jelas membutuhkan penelitian, sehingga bisa jadi terpenuhinya dan bisa pula tidak.
[3]. Mimpi sendiri terbagi-bagi. Ada mimpi yang merupakan mimpi biasa yang datangnya dari syetan; ada yang merupakan khayalan; dan ada juga yang merupakan rekaman peristiwa yang terjadi sebelum tidur. Kapan kita bisa menentukan mimpi yang benar sehingga bisa diambil sebagai patokan hukum dan mana mimpi yang tidak benar untuk kita tinggalkan?
Mimpi yang menggambarkan Rasulullah mengabarkan tentang suatu hukum pun perlu dilihat. Bila (di dalam mimpi orang tersebut) beliau mengabarkan tentang suatu hukum yang sesuai dengan syari’at, maka (pada hakekatnya) hukum yang dipegang adalah hukum yang telah ada (dalam syari’at) tersebut. Dan jika beliau mengabarkan tentang sesuatu yang menyelisihi (syari’at), maka itu mustahil. Karena setelah Rasulullah wafat, syari’at yang telah ditetapkan semasa hidupnya tidak akan manshukh (diganti dengan yang lainnya). Sebab agama Islam ini, meskipun Rasulullah telah wafat, ketetapan hukumnya tidak akan berubah dengan sebab mimpi seseorang. Karena hal itu suatu kebatilan menurut ijma’. Jadi barang siapa yang bermimpi (mendapati Rasulullah mengabarkan suatu hukum yang bertentangan dengan syari’at yang telah ada) itu, maka tidak boleh diamalkan. Dan pada saat tersebut kita katakana: Mimpi orang tersebut tidak benar. Karena kalau dia benar-benar (bermimpi) melihat Rasulullah, tentu beliau tidak akan mengabarkan sesuatu yang menyelisihi syari’at.
Sekarang, mari kita bicarakan makna sabda Rasulullah
“Barangsiapa yang melihatku di waktu tidur, berarti ia telah melihatku.”
Dalam hal ini ada dua penafsiran, yaitu.
Pertama.
Makna hadist tersebut (adalah):
"Barangsiapa(bermimpi) melihatku sesuai bentuk di mana aku diciptakan maka ia telah melihatku; karena syetan tidak bisa menyerupaiku.”
Karena beliau tidak mengatakan, “Barang siapa yang berpendapat bahwa dia melihatku (dalam mimpi), maka dia telah melihatku”, tetapi mengatakan, “Barangsiapa melihatku (dalam mimpi) maka dia telah melihatku”. Darimana orang yang berpendapat bahwa dirinya melihat Rasulullah itu memastikan kalau yang dia lihat dalam mimpinya itu betul-betul wujud beliau? Jika dia tetap (bersikeras) telah melihat beliau, padahal dia tidak bisa memastikan kalau yang dilihatnya itu adalah betul-betul wujud beliau, maka ini adalah sesuatu yang sulit untuk dipercaya.
Kesimpulannya: Apa yang dilihat dalam mimpi seseorang bisa saja bukan Rasulullah, meskipun orang yang bermimpi meyakini bahwa itu adalah beliau.
Kedua.
Para ahli ta’bir mimpi berkata, “sesungguhnya syetan bisa mendatangi seseorang yang sedang tidur dalam bentuk tertentu, seperti dalam bentuk orang yang dikenal oleh yang bermimpi tersebut atau yang lainnya. Lalu (syetan) menunjukkannya kepada orang lain (sambil berkata): ‘Fulan ini adalah Nabi!’ Cara seperti itulah yang ditempuh syetan dalam menjalankan tipu dayanya terhadap orang yang bermimpi. Padahal, sosok Nabi mempunyai tanda-tanda tertentu. Kemudian, sosok yang ditunjukkan oleh syetan tersebut menyampaikan perintah atau larangan yang tidak sesuai dengan syari’at kepada orang (yang bermimpi). Orang yang bermimpi itu mengira kalau itu dari Rasulullah, padahal bukan, sehingga ucapan, perintah, atau larangan yang disampaikan dalam mimpi itu tidak boleh kita percaya.”
Jadi, jelaslah sudah permasalahan ini. Yaitu, bahwa suatu hukum tidak bisa diambil dari mimpi-mimpi sebelum dicocokkan terlebih dahulu dengan dalil, karena gambaran yang ada dalam mimpi kemungkinan tercampur dengan kebatilan.
Hanya orang-orang yang lemah hatinya sajalah yang berdalil dengan mimpi dalam masalah hukum-hukum (syar’i). Memang, bisa saja orang yang dilihat (dalam mimpi) itu datang dengan membawa pemberitahuan, kabar gembira, maupun peringatan secara khusus, akan tetapi para ahli ta’bir mimpi itu tidak menjadikannya sebagai pedoman dalam menentukan hukum dan membangun suatu kaidah. Memang sikap yang benar dalam menyikapi apa yang terlihat dalam mimpi adalah dengan selalu berpatokan dengan syari’at yang ada, wallahu a’lam.
Barangsiapa yang memperhatikan cara ahli bid’ah dalam berdalil, niscaya dia akan mengetahui bahwa mereka itu tidak memiliki alasan yang mapan. Karena alasan-alasan mereka itu terus saja mengalir berubah-ubah, tidak akan pernah berhenti pada satu alas an tertentu. Dan berdasarkan alasan-alasan itulah, orang-orang yang menyimpang dan orang-orang kafir mendasarkan penyimpanmgan dan kekufurannya, serta menisbatkan ajarannya itu kepada syari’at.
Barangsiapa yang tidak ingin terperosok ke dalam tindakan semacam itu, hendaknya mencari kejelasan jalan mana yang lurus baginya. Karena siapa yang berani meremehkan (hal ini), niscaya tangan-tangan hawa nafsu akan melemparkan kedalam berbagai kebinasaan yang tiada seorang pun dapat membebaskannya, kecuali bila Allah menghendaki lain.
[Disalin dari “Kutaib Muhtashar Al-I’tisham, Peringkas Syaikh Alawi bin Abdul Qadir As-Saqqaf, Penulis Abu Ishaq Ibrahim bin Musa ASy-Syathibi, Edisi Indonesia Ringkasan Al-I'tishom Imam Asy-Syathibi, Penerjemah Arif Syarifuddin, Penerbit Media Hidayah]
Sumber : http://www.almanhaj.or.id/content/1920/slash/1














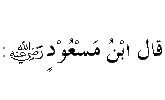




















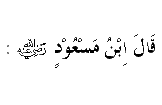














Comments (0)
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.